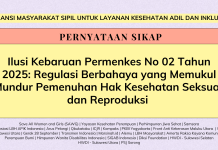Beberapa waktu terakhir ini, telinga kita tentu akrab dengan istilah persekusi; terutama setelah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh—saat itu—Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Singkat kata, ‘persekusi’ merupakan sebuah gerakan yang digalakkan oleh ekstrimis Islam (mari kita tidak merujuk pada salah satu organisasi untuk menghindari persekusi saat membahas persekusi) dengan memberikan hukuman berupa kekerasan, baik fisik, verbal, maupun ancaman di dunia maya, terhadap orang-orang yang dianggap telah mencemooh ulama dalam aktivitasnya di dunia maya. Tapi, sebenarnya apa, sih, yang dimaksud dengan persekusi itu?
Bila kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi merupakan verba yang dapat diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Sementara bila kita merujuk pada Merriam-Webster, persekusi yang diambil dari kata persecution ditempatkan sebagai sebuah noun dengan makna sebuah tindakan untuk melecehkan atau menghukum dengan tujuan untuk melukai, membuat sedih, atau merundung terutama terhadap mereka yang berbeda asal-usul, agama ataupun pandangan sosialnya.
Dari dua definisi di atas, kita tahu bahwa tindakan persekusi memiliki sifat yang negatif. Sebuah tindakan yang mungkin tidak akan diajarkan pada anak-anak kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena akan digolongkan dalam tindakan-tindakan yang melukai moral kita dalam berbangsa dan bernegara. Lantas, bila kita semua setuju dengan difinisi itu—dan setuju juga untuk memberi label negatif pada tindakan tersebut, mengapa tindakan-tindakan persekusi ini marak terjadi selama beberapa waktu terakhir? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita kembali pada definisi persekusi itu sendiri yang sudah dipaparkan di paragraf sebelum ini.
Nah, coba cermati kata-kata yang dicetak tebal pada paragraf di atas.
Sewenang-wenang. Beberapa orang, sekalipun mengerti sifat negatif yang dibebankan pada tindakan ini, berpendapat bahwa persekusi harus dilakukan, terutama dengan sewenang-wenang. Kenapa? Karena bila tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, bila persekusi harus dilakukan dengan alur hukum yang benar, mereka yang menjadi target persekusi tidak akan pernah mendapatkan hukuman. Alasan ini bukanlah alasan yang dibuat-buat, setidaknya itulah yang coba disampaikan oleh Sugito, Ketua Bantuan Hukum FPI, yang kemudian memberi paparan, “Kan, tahu sendiri, kalau Ahok melapor langsung diproses. Kalau kita yang melapor harus berjuang dulu baru diproses. Kalau yang terkait dengan penghinaan ulama, yang sekarang ini, yang terakhir ini, lah. Jarang, lah. Jarang diproses.”
Terlepas dari benar-tidaknya polisi jarang memproses laporan mengenai penghinaan terhadap ulama, alasan ini kemudian dianggap sebagai alasan yang valid bagi ekstrimis Islam untuk melakukan persekusi. Andaikan kasusnya bukan persekusi, dan pelakunya bukan seorang ekstrimis agama apapun, tentu tak sedikit pula yang setuju dengan tindakan main hakim sendiri. ‘Biar kapok!’, misalnya, adalah satu dari banyak argumen bersifat apologetik yang akan kita amini—dan nyatanya kita memang jarang dengan kencang bersuara saat masyarakat main hakim sendiri untuk pelaku begal, geng motor, pemerkosa atau tindakan-tindakan kriminal lainnya.
Tervalidasi ataupun tidak, persekusi sudah terjadi. Sejak 27 Januari 2017 hingga 31 Mei 2017 saja, Damar Juniarto dari SAFEnet melaporkan sudah ada 59 orang yang menjadi target persekusi. Anda tentu sempat membaca berita soal remaja 15 tahun yang dianiaya secara verbal dan fisik di Tangerang atas nama persekusi ini hingga harus dievakuasi oleh polisi. Atau mungkin kasus persekusi yang menimpa Fiera Lovita di Solok setelah dia dituduh menghina salah satu ulama melalui komentarnya di media sosial. Bila persekusi ini terus terjadi, kita akan membaca berita mengenai 57 orang lainnya yang menjadi target persekusi. Depresif sekali rasanya.
Pertanyaannya adalah, apakah persekusi ini sebuah tindakan yang salah? Kita, bersama dengan KBBI dan Merriam-Webster mungkin menganggapnya demikian, namun bagi pelakunya mungkin tidak demikian. Mengapa tidak? Karena mereka memang tidak menganggap persekusi ini sesuatu yang salah. Dalih membela agama menjadi validasi yang sempurna bagi mereka, karena … bagaimana mungkin sebuah tindakan untuk membela agama disebut sebagai tindakan yang salah, kan?
Mengenai dalih bela agama ini, mau tidak mau kita harus berkaca pada kasus penikaman yang terjadi di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Alkisah di hari pertama Ramadan yang jatuh di akhir Mei lalu, dua orang perempuan—seorang di antaranya mengenakan hijab—tengah berada di dalam gerbong kereta ketika Jeremy Joseph Christian, 35 tahun, mulai melakukan kekerasan verbal kepada keduanya (kegiatan aktivitas anti-Islam yang memang sedang tren di Amerika sana semenjak Donald Trump terpilih sebagai presiden). Tiga orang laki-laki di kereta tersebut tak setuju dengan Jeremy, mereka berdiri dan membela dua orang perempuan yang dilecehkan oleh Jeremy. Tak butuh waktu lama sampai Jeremy akhirnya melakukan kekerasan fisik, ia menikam tiga laki-laki yang menghalanginya melecehkan perempuan muslim tersebut. Dari tiga orang laki-laki yang mencoba menengahi Jeremy, dua meninggal dan satu terluka.
Bicara tentang persekusi, di bagian mana kita harus berkaca pada kasus Jeremy Joseph Christian? Di bagian berikut …
Pada persidangan pertamanya, Jeremy Joseph Christian dengan lantang berteriak, “You call it terrorism, I call it patriotism. You got no safe place! Death to the enemies of America!” Tentunya, ekstrimis Islam tidak mau disamakan dengan seseorang bernama Christian yang anti terhadap Islam, kan? Tapi, mau tidak mau, kita akan berpikir bahwa ‘kamu menyebutnya terorisme, aku menyebutnya patriotisme’ akan terdengar senada dengan ‘kamu menyebut persekusi kriminal, aku menyebutnya bela agama.’