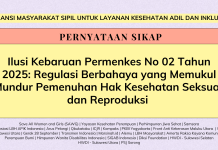Seiring maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, telinga kita juga semakin akrab dengan istilah rape culture atau budaya perkosaan. Dianne F. Herman, sosiolog sekaligus pencetus istilah budaya perkosaan, mendefinisikannya sebagai kebudayaan di mana kekerasan dan seksualitas saling terkait. Prakteknya bisa sesederhana kata-kata seksis yang dilontarkan kepada perempuan, misalnya “Hai cewek, godain kita dong!” Atau sikap permisif masyarakat menghadapi pelecehan seksual yang dilakukan pria, seperti kalimat “Wajarlah, cowok memang begitu”. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, adanya nilai-nilai diskriminatif yang diterima sebagai kewajaran, misalnya soal konsep keperawanan juga memperlemah posisi perempuan.
Lho, memang apa hubungannya keperawanan dengan budaya perkosaan? Konsep keperawanan yang kita kenal menekankan bahwa semua perempuan terlahir dengan selaput dara. Karena itu perempuan ‘baik-baik’ wajib membuktikan keutuhan selaput daranya pada pasangan. Mitos yang banyak diterima adalah selaput dara yang masih utuh akan robek dan berdarah saat pertama kali melakukan hubungan seksual.. Pembuktian keperawanan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat, bahkan kadang lebih penting dibanding pribadi perempuan sebagai individu itu sendiri. Akibatnya, pria merasa hebat dan berkuasa ketika berhasil ‘mendapatkan’ keperawanan ini sekalipun dengan jalan kekerasan. Inilah yang kemudian menempatkan perempuan sebagai subordinat lelaki.
Bagaimana dengan perempuan yang selaput daranya sudah tidak utuh namun belum menikah? Mereka akan mendapat stigma sebagai kaum tidak bermoral, sehingga masyarakat merasa berhak memperlakukan mereka dengan semena-mena. Dalam sebuah wawancara menarik untuk penelitian terkait kondisi psikologis pemerkosa di Jurnal Perempuan. Dalam wawancara itu, ibu seorang pelaku perkosaan mengungkapkan protesnya atas hukuman yang diterima anaknya. Di mata sang ibu, hukuman yang diterima putranya sangat berlebihan karena perempuan yang diperkosa sudah tidak perawan. Pada kesempatan lain, seorang pelaku perkosaan juga mengaku tidak merasa bersalah karena yang ia lakukan “hanya usaha membuktikan keperawanan sang kekasih”. Kedua ilustrasi ini merupakan gambaran jelas bahwa kita tak akan bisa menghapus tindak pemerkosaan tanpa menghapus rape culture terlebih dahulu. Untuk itu pertama-tama kita perlu mengubah cara pandang masyarakat tentang keperawanan sebagai sesuatu yang kodrati.
Merubah perspektif sosial yang diskriminatif, seksis dan misoginistik terkait keperawanan tentu tidaklah mudah. Namun kita bisa melakukannya melalui pendidikan yang bukan sekadar membahas fungsi-fungsi biologis manusia dan moral semata, tapi juga tentang kesetaraan gender. Untuk itu, kita juga perlu mengubah pola pikir kita tentang kodrat, termasuk kodrat biologis. Hal ini memang jauh dari mudah, namun bukankah pendidikan dan karir yang kita nikmati sekarang adalah bukti bahwa konsep kodrat tak bisa lagi kita jadikan pegangan?
Penulis : Caecilia Purnamasari
Editor : Wita Ayodhyaputri