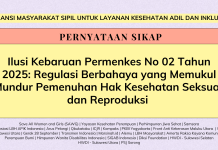Sama seperti ‘hear’ dan ‘listen’ pada bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengenal ‘mendengar’ dan ‘menyimak’. Namun, di antara banyak suara yang ingin didengarkan, suara mana yang harus kita dengar? Kemudian, dengan cara bagaimana kita harus mendengarkan suara-suara yang perlu didengar tersebut?
Active Listening tidak hanya sekadar mendengarkan, bahkan lebih dalam lagi dibanding menyimak. Mengapa kita perlu melakukan active listening? Ketika dihadapkan pada pertanyaan tersebut, banyak di antara kita yang mungkin tertegun dan bingung; kami di Samsara juga mengalami hal yang sama. Dengan menerjemahkan ‘active’ dan ‘listening’ secara terpisah, bisa jadi kita sudah bisa menebak-nebak mengapa kita perlu mempraktikkan active listening. Tetapi saat diharuskan untuk memikirkan dengan lebih mendalam, benar-benar merenungkannya, jawabannya akan sangat menarik untuk dibagikan.
Silakan menikmati renungan salah satu staf Samsara mengenai Active Listening berikut:
“The sense that we are not being listened to is one of the most frustrating feelings imaginable. Toddlers scream about it, teenagers move out, couples split up, companies breakdown.”
Kalimat pembuka di artikel ini sangat mengena di hati saya karena saya sudah mengalami semuanya. Memang sangat membuat frustasi ketika kita merasa tidak didengarkan atau dibuat menjadi bungkam. Saya merasa hal ini masih terjadi di kehidupan saya pada aspek-aspek tertentu, tapi saya mencoba membenahinya. Namun, pembenahan ini menjadi sulit saat kita merasa lawan bicara kita tidak berada dalam keadaan yang sama, yaitu menginginkan terjadinya pembenahan dan perubahan.
Pembenahan dan perubahan hanya bisa terjadi jika kita mau menghadapi ketakutan terbesar kita. Banyak orang, termasuk saya, dan mungkin juga Anda, tidak ingin dihadapkan pada ketakutan terbesar kita. Saya pernah mencoba memasuki relung hati saya yang paling dalam, dan bertanya pada diri saya sendiri, “Apa sesungguhnya ketakutan terbesar saya?” Saya tidak menyangka bahwa dengan pertanyaan itu, saya akan dibawa ke tempat paling rapuh dalam diri saya. Saya tidak menyukai perasaan itu. Namun, di saat yang bersamaan, saya menyadari bahwa bila saya terus menghindari memasuki tempat tersebut, saya tidak akan tahu hal yang justru bisa membuat saya berkembang secara personal. Saya sudah mendatangi beberapa psikolog dan saya bisa katakan bahwa ucapan mereka tidak ada gunanya bila kita masih hidup di dalam penyangkalan diri. Lalu saya tahu, langkah awal saya dalam menangani masalah saya adalah dengan mengakui semua hal ke diri sendiri, termasuk ketakutan saya.
Saya belum bisa mengatakan bahwa saya sudah berhasil, saya bahkan tidak tahu indikator keberhasilannya. Tapi setidaknya, mulai ada perasaan lega merayap di relung hati saya. Saya bermaksud menjadikan ini sebagai kebiasaan dengan membuatnya menjadi budaya saya, nilai yang saya anut untuk diri saya sendiri.
Kembali pada active listening. Mencermati definisinya, saya akui tadinya saya termasuk orang yang berpikir bahwa kemampuan orang untuk mendengarkan dengan baik adalah bakat alami dari Tuhan, bawaan sejak lahir. Membaca artikel ini menyadarkan saya bahwa itu adalah skill yang bisa dipelajari dan dilatih. Namun saya merasa lelah bila hanya saya yang memahami ini dan mempraktikkannya. Bagaimana dengan lawan bicara kita yang dengannya, kita cukup intens berbicara? Maukah dia belajar bersama kita? Kita tentu tidak akan tahu jawabannya bila kita tidak menanyakannya secara langsung kepada yang bersangkutan, bukan? Namun untuk menanyakannya kita sudah terpenjara dengan asumsi-asumsi mengenai respon yang akan kita dapatkan. Karena, sekali lagi saya katakan, tidak mudah meminta orang untuk mengenali dan menghadapi ketakutan terbesar mereka. Meski bila itu syarat utama jika kita ingin ada pencapaian dan perkembangan yang lebih besar di dalam diri kita.
Kemudian, bagaimana dengan lawan bicara yang merasa bahwa dia sudah mempraktikkan active listening—terlepas dia paham definisi active listening atau tidak—namun sebenarnya dia tidak melakukannya. Menurut saya, justru di sini skill kita sebagai lawan bicaranya dituntut lebih prima. Semua orang tentu tidak selalu berada dalam keadaan terbaiknya, kan? Di sinilah potensi-potensi konflik bisa terjadi. Konflik pasti terjadi, cepat atau lambat, pada kita dan orang-orang di sekitar kita yang berkomunikasi secara intens dengan kita. Itu wajar dan alami sekali. Namun, bagaimana mengolah konflik tersebut agar bisa tetap konstruktif? Kedewasaan dan kebijakan pihak-pihak yang berkonflik tentu diperlukan. Kadang juga, kita lebih bisa mempraktikkan active listening pada orang yang menjadi mediator konflik kita karena kita percaya pada kenetralannya. Mungkin, yang diinginkan semua orang adalah sama; keterangan, kejelasan dan keadilan. Pertanyaannya, mampukah kita melakukannya?