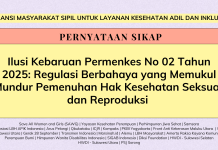Bagaimana aku harus menuliskannya? Aku pun masih belajar untuk mengatakan ini tanpa membuat perempuan yang sedang marah merasa kemarahannya diinvalidasi, atau tanpa membuat siapa saja yang tidak sedang marah menjadi marah karena tidak setuju dengan apa yang ingin kusampaikan. Yah, isi kepala adalah hak masing-masing, kan? Aku ingin memulai dengan permintaan maaf, tapi aku tak merasa perlu meminta maaf atas apa-apa saja yang ada di pikiranku. Seperti yang sebelumnya kukatakan, isi kepala adalah hak masing-masing. Mungkin permintaan maaf diperlukan karena aku menuliskan pemikiranku dan membiarkan tulisan ini sampai pada kalian –yang mungkin sebagian besar tak setuju dengan isinya. Aku tak bermaksud menginvalidasi kemarahan siapapun. Aku tak bermaksud memaksa siapapun mengamini nilai dan apa-apa saja yang kupercaya. Aku menulis karena aku merasa perlu melakukannya.
Tumbuh dalam kultur yang memuliakan pernikahan sebagai sebuah ikatan luhur maupun tujuan akhir dari relasi percintaan bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi perempuan. Sebaliknya, itu jauh dari kata mudah. Sejak kecil, aku, atau mungkin kita telah dibiasakan untuk melihat pernikahan hanya dari satu sudut pandang: baik. Mungkin aku terlalu menyederhanakan kata baik itu sendiri, tapi aku tidak lagi dapat menemukan satu kata yang cukup tepat untuk mendeskripsikan makna pernikahan yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat tempat aku –tempat kita– dibesarkan.
Ya, pernikahan adalah sesuatu yang baik, maka semua yang buruk akan menjadi baik dengan pernikahan. Itu adalah konsep berpikir yang terus-menerus ditanamkan dalam kepala kita, dibiarkan mengakar sampai ke alam bawah sadar, lalu lambat laun mengubah kita menjadi salah satu dari mereka. Tentu saja, berikutnya kita akan mewariskan konsep yang sama pada anak, cucu, cicit, anak dari cicit, dan seterusnya.
Penyederhanaan makna pernikahan pada akhirnya akan memunculkan masalah-masalah baru. Mari kita bicara dalam konteks situasi kehamilan tidak direncanakan, misalnya. Perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan bukannya tidak memiliki pilihan. Tentu saja pilihan itu ada, dan perempuan berhak menentukan pilihan terbaik untuk tubuh dan dirinya tanpa tekanan dari pihak manapun. Pernikahan adalah salah satu pilihan dalam situasi kehamilan tidak direncanakan.
Lainnya, perempuan dapat memutuskan melanjutkan kehamilan tanpa menikah, mengadopsikan anaknya, atau menghentikan kehamilan dengan prosedur aborsi aman. Pertanyaannya, mengapa di antara semua pilihan, hanya pernikahan yang selalu dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban?
Aku sudah sampaikan di awal bahwa kita telah dibiasakan untuk memandang pernikahan sebagai sesuatu yang baik dan yang tidak aku sampaikan di awal adalah bahwa adopsi dan aborsi merupakan tindakan yang memiliki stigmanya masing-masing. Hal itulah yang membuat pernikahan hampir selalu menjadi pilihan dominan, suka atau tidak.
Cara pandang masyarakat terhadap pernikahan membuat pernikahan itu menjadi pilihan yang paling minim stigma ketimbang pilihan-pilihan yang lain, namun tidak lantas membuatnya minim risiko. Alih-alih menyelesaikan masalah terkait kehamilan tidak direncanakan, menikah dengan kondisi tanpa persiapan dan pertimbangan matang justru akan menimbulkan masalah-masalah lain di kemudian hari, mulai dari kesulitan ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Apakah risiko-risiko itu sepadan untuk apa yang kita sebut sebagai sebuah tindakan pertanggungjawaban? Aku rasa tidak. Pernikahan yang seperti itu menurutku bukan lagi bentuk tanggung jawab, tapi penghukuman.
Kita perlu mulai membuka diri pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang lain dalam situasi kehamilan tidak direncanakan, keluar dari doktrin nenek moyang tentang kemuliaan pernikahan. Adopsi dan aborsi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban. Kita harus memperhitungkan peran adopsi dalam mencegah penelantaran anak dan mengurangi kasus gizi buruk pada anak. Sama halnya kita juga harus mempertimbangkan tindakan aborsi aman sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan depresi pospartum serta menekan lonjakan populasi.
Setiap pilihan sama baiknya sebagaimana setiap pilihan punya risikonya masing-masing. Toh, bukankah sebenarnya pertanggungjawaban yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri? Maka buatlah keputusan yang terbaik untuk diri kita tanpa perlu merasa bersalah pada siapapun.
Aku percaya semua pilihan baik adanya saat diambil dengan penuh pertimbangan dan kesiapan. Hal terpenting adalah memastikan setiap pilihan yang diambil dalam situasi kehamilan tidak direncanakan diputuskan sendiri oleh perempuan yang mengalami kehamilan, tanpa tekanan dari siapapun.
Aku sangat paham bahwa perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan tentu saja tidak ingin menanggung semuanya sendirian, terutama jika memiliki pasangan. Tapi sekali lagi aku tegaskan, pernikahan bukanlah penyelesaian! Pernikahan bukan satu-satunya cara untuk menagih kontribusi pasangan saat mengalami kehamilan tidak direncanakan.
Sebagaimana perempuan, lelaki yang berada dalam situasi kehamilan tidak direncanakan punya banyak pilihan untuk mendukung keputusan pasangannya. Misalnya dengan menemani dan memberikan dukungan emosional saat pasangan memilih untuk aborsi, atau membantu pengurusan berkas saat pasangan memilih adopsi, bahkan memberikan dukungan finansial saat pasangan memilih melanjutkan kehamilan tanpa menikah. Ada banyak cara, maka jangan jadikan pernikahan sebagai alasan untuk sekadar memberi makan ego kita, apalagi ego orang-orang di sekitar kita.