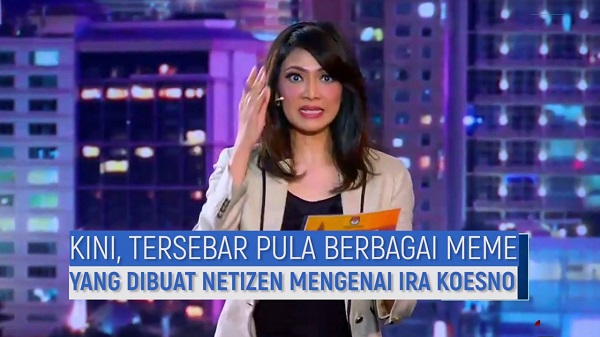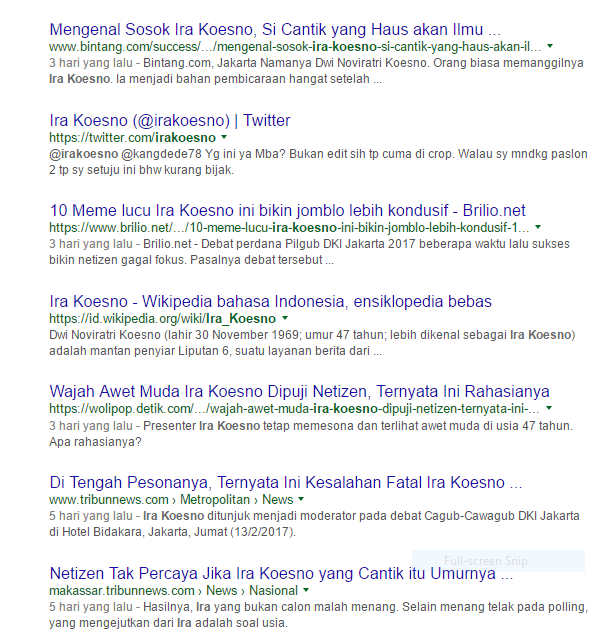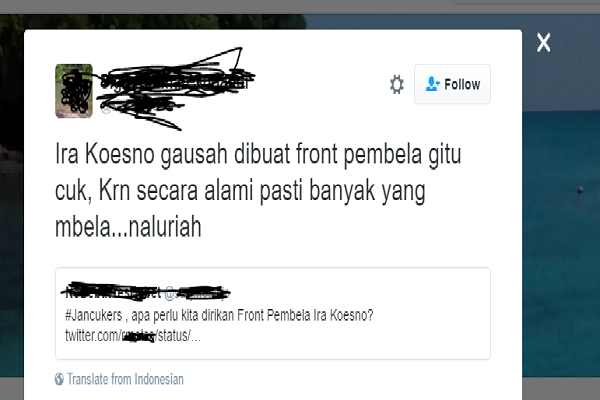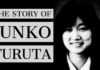She just wants to be beautiful;
she goes unnoticed, she knows no limit.
Baris di atas merupakan pembuka untuk lagu ‘Scars to Your Beautiful’ yang dinyanyikan oleh Alessia Cara. Dari judulnya saja, tentu sudah banyak yang sempat menduga bahwa single ketiga dalam album ‘Know-It-All’ ini akan bercerita tentang body image. Alessia Cara sendiri, ketika diwawancarai di akhir Mei 2016, menjelaskan bahwa pada dasarnya lagu ini memang tentang body image.
Sebenarnya, Scars to Your Beautiful bukanlah lagu pertama yang bertutur tentang body image. Hampir delapan belas tahun lalu, tanggal 10 Agustus 1999, TLC merilis ‘Unpretty’ yang mengakui adanya kecantikan dalam sebuah ketidaksempurnaan, baik yang terlihat maupun tidak. Beberapa tahun yang lalu (2014), Meghan Trainor juga mempromosikan body positive dalam ‘All About that Bass’. Beyoncé pun tak jarang merilis lagu-lagu bertema body image. Lalu, apa yang membuat Scars to Your Beautiful menjadi menarik untuk dibahas?
Dalam lagunya, Alessia Cara melakukan pendekatan yang menarik untuk mengampanyekan pentingnya mencintai diri sendiri—dengan apa adanya dan juga untuk segala apa yang tidak ada padanya. Gadis kelahiran tahun 1996 ini memilih menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menceritakan kisah seorang gadis yang begitu ‘terobsesi’ dengan standar kecantikan yang digelontorkan oleh para covergirls. Sebagian dari kita mungkin akan menertawakan obsesi yang tidak sehat tersebut. Bagaimana tidak? Bila dipikir-pikir, betapa bodohnya orang yang begitu terobsesi dengan ‘postur Barbie’ yang hanya sekadar rekaan industri kosmetik. Bahwa perempuan harus cantik, bahwa cantik harus putih, dan bahwa-bahwa lainnya yang kita tahu memang sengaja dibuat supaya produk-produk kosmetik yang mereka jual terus dibeli.
Menyadari bagaimana kita menertawakan—dan terutama meremehkan—mereka yang hanya mengejar standar kecantikan artifisial tersebut, Alessia Cara seolah menampar kita dengan Scars to Your Beautiful. Sekencang-kencangnya. Alessia Cara seolah ingin menunjukkan bahwa mereka yang terobsesi dengan standar kecantikan tersebut memang benar-benar ada; dan sekalipun kita terus menertawakan atau meremehkan mereka, bukan berarti mereka akan berhenti mengejar standar kecantikan. Justru dengan meremehkan mereka, kita malah berusaha melakukan simplifikasi terhadap masalah yang ada. Menganggap masalah tersebut bukanlah sesuatu yang serius.
So she’s starving, you know,
“Covergirls eat nothing,” she says, “Beauty is pain
and there’s beauty in everything. What’s a little bit of hunger?
I can go a little while longer,” she fades away
Kita terlalu sibuk tertawa dan meremehkan sehingga luput dalam menyadari bahwa untuk mengejar sebuah standar kecantikan, ada orang-orang yang rela untuk kelaparan, dan terus-menerus kelaparan hingga akhirnya menghilang. Entah Alessia Cara yang kurang keras dalam menampar atau memang kulit kita yang terlalu tebal jika kita masih tertawa di poin ini. Tentu, Alessia Cara sendiri mungkin tak bermaksud menghakimi kita yang masih terus tertawa dan meremehkan. Yang mengagumkan dari Alessia Cara adalah kesediaannya—yang dituangkannya dalam baris-baris selanjutnya—dalam membantu mereka yang tersakiti oleh standar kecantikan ini untuk melihat bahwa kecantikan bukan hanya tentang apa yang terlihat saja. Sebuah kesediaan yang sebenarnya kembali menampar kita untuk mencoba melakukan hal yang sama.

Kualitas ini, bisa dibilang, merupakan satu hal yang membuat Scars to Your Beautiful berbeda dari kebanyakan lagu tentang body image. Narasi yang coba dibangun oleh Alessia Cara bukan hanya tentang bagaimana kita melihat ke dalam dirinya, jauh lebih dalam dari penampakan luar yang distandarisasi dengan standar kecantikan, untuk menemukan bahwa kita semua merupakan seorang bintang dan kita semua bersinar sama cantiknya. Alessia Cara juga mencoba membangun sebuah narasi tentang bagaimana kita sebaiknya berhenti tertawa dan meremehkan dan mulai mengubah cara pandang kita terhadap cara orang lain memandang kecantikan, alih-alih memaksa seseorang berubah—baik berubah dan memenuhi standar kecantikan atau berubah agar tak lagi terobsesi dengan standar kecantikan tersebut.
* * *
Pada tahun 1964, Kitty Genovese ditikam sampai mati di luar apartemennya di New York sementara bystander yang melihat hanya sekadar mengamati kejadian tersebut tanpa sedikitpun berusaha menolong maupun memanggil polisi. Bila masing-masing dari kita adalah bintang utama untuk kehidupan kita sendiri, bisa dibilang masing-masing dari kita juga merupakan bystander di kehidupan masing-masing yang lainnya. Akankah kita menolong ‘Kitty-Kitty modern’ yang ditikam oleh standar kecantikan di depan mata kita, atau lagi-lagi hanya sekadar mengamati—meskipun tidak lagi tertawa?
You don’t have to change a thing,
the world could change its heart
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MWASeaYuHZo]
 POPCORNer. Merupakan sebuah sudut di Samsara yang dikhususkan untuk mengulas produk-produk budaya pop dengan kacamata feminisme. Kamu bisa mengusulkan produk budaya pop apa lagi yang perlu kita ulas berikutnya. POPCORNer terbit setiap Sabtu. POPCORNer. Merupakan sebuah sudut di Samsara yang dikhususkan untuk mengulas produk-produk budaya pop dengan kacamata feminisme. Kamu bisa mengusulkan produk budaya pop apa lagi yang perlu kita ulas berikutnya. POPCORNer terbit setiap Sabtu. |


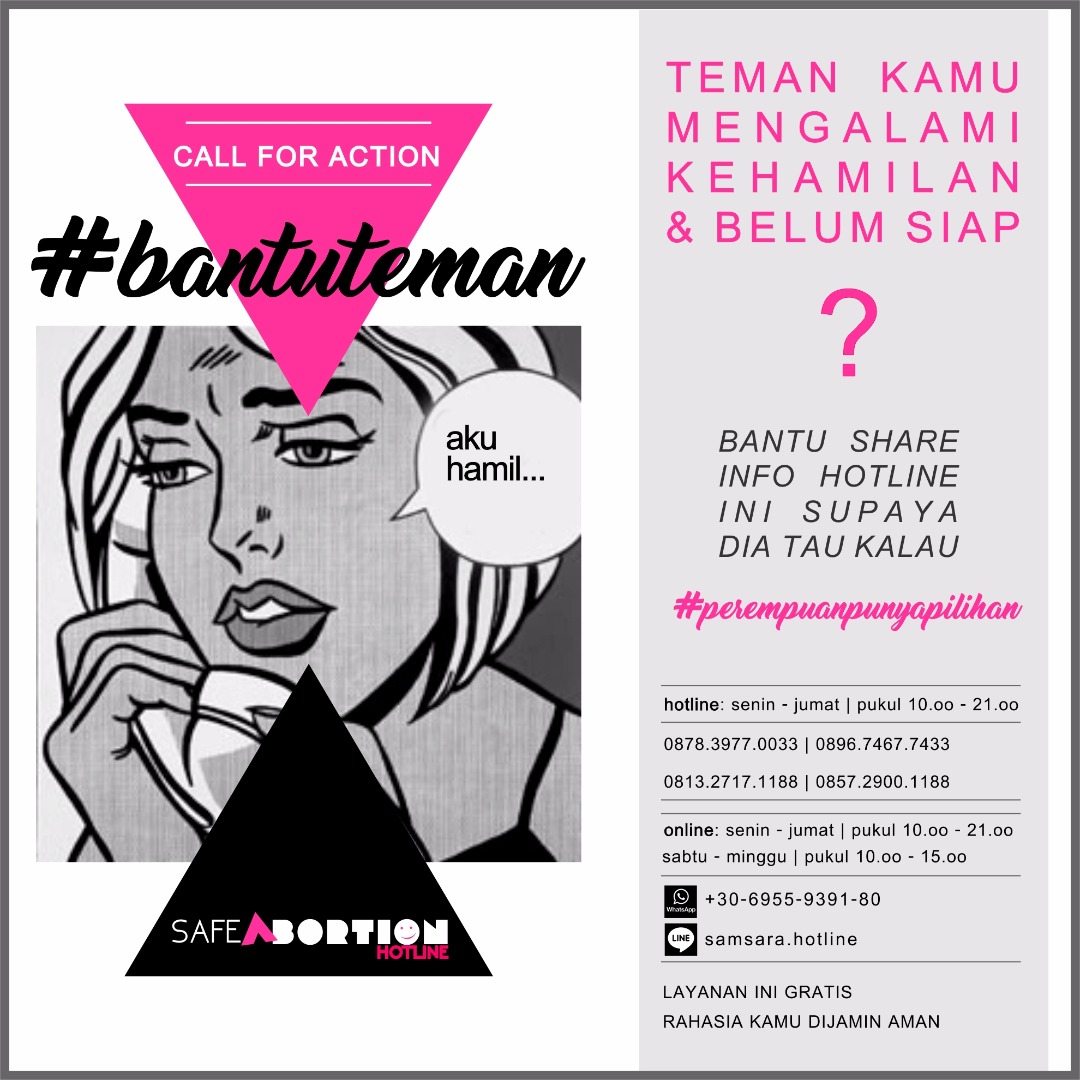
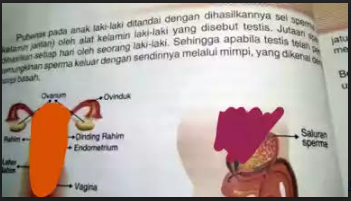
 Medda Maya Pravita. Perempuan, peneliti, penghayat astrologi.
Medda Maya Pravita. Perempuan, peneliti, penghayat astrologi.



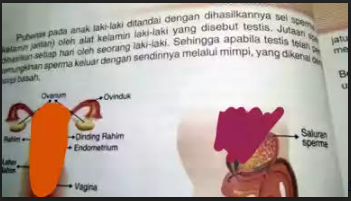
 Amanda Kistilensa adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kedua orang tuanya aktif berkiprah dalam ranah politik. Dalam kesehariannya, Amanda bekerja sebagai seorang penerjemah dan berusaha menjalani hidup dengan damai sebagai seorang feminis.
Amanda Kistilensa adalah anak kedua dari empat bersaudara. Kedua orang tuanya aktif berkiprah dalam ranah politik. Dalam kesehariannya, Amanda bekerja sebagai seorang penerjemah dan berusaha menjalani hidup dengan damai sebagai seorang feminis.