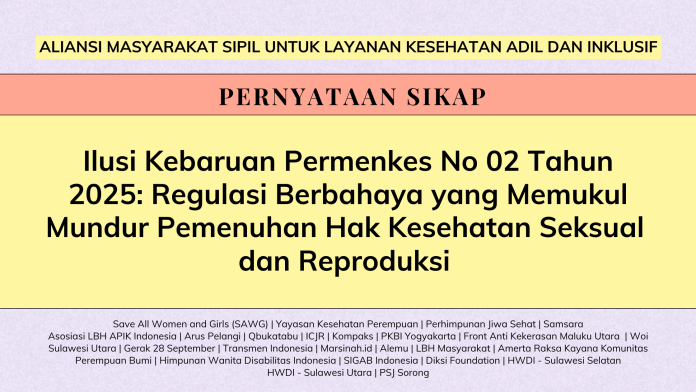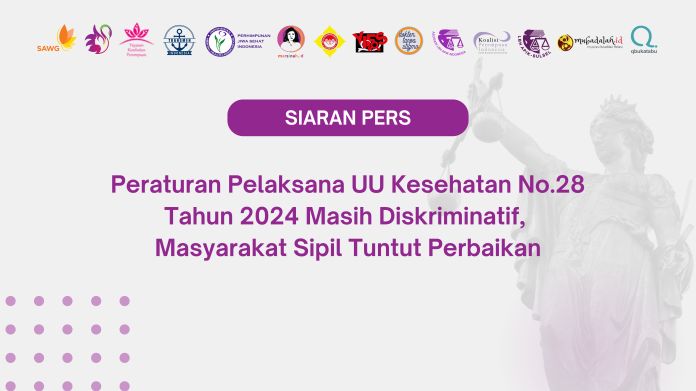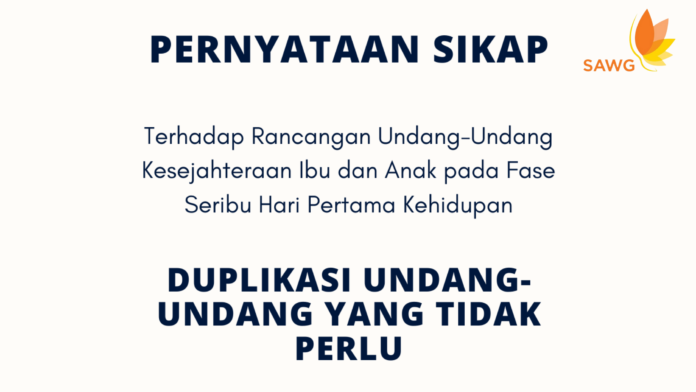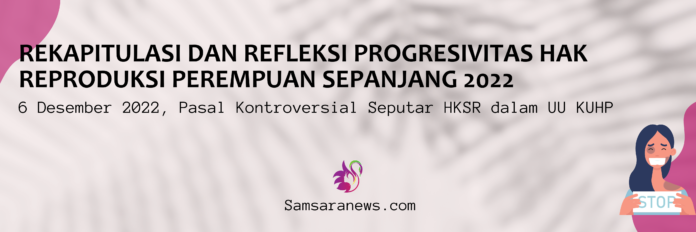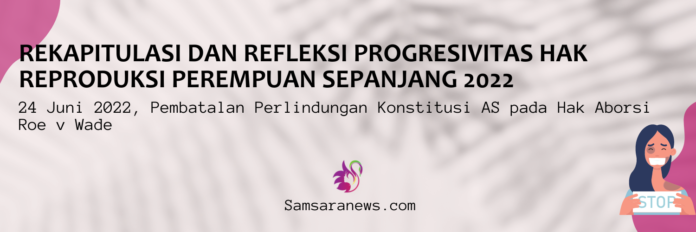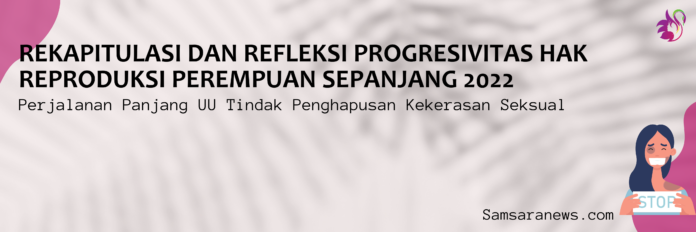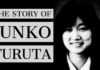Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan Adil dan Inklusi
06 Maret 2025
Kami, aliansi masyarakat sipil yang konsisten mengawal perkembangan aturan turunan pada UU Kesehatan No.17 Tahun 2023 serta aktif memberikan masukan pada proses penyusunan aturan turunan guna mendapatkan akses layanan yang adil dan inklusif¹, menyatakan keberatan atas substansi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.02 tahun 2025. Keberatan ini utamanya kami tujukan pada pasal-pasal diskriminatif yang justru mencederai perlindungan kelompok rentan, menghilangkan otonomi tubuh tiap individu, serta menjauhkan korban dari akses layanan kesehatan yang terjangkau dan memulihkan.
Secara substansi, PMK No.2 Tahun 2025 ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat 4 UU Kesehatan No.17 Tahun 2023, yang mengamanatkan Negara–baik Pemerintah Pusat maupun Daerah–wajib menyediakan layanan kesehatan primer dan lanjutan bagi masyarakat rentan dengan prinsip inklusif non-diskriminatif. Kelompok ini mencakup individu yang termarjinalisasi secara sosial, baik berdasarkan agama/kepercayaan, ras atau suku, disabilitas, orientasi seksual dan identitas gender, serta individu yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
Proses Penyusunan yang Tidak Partisipatif
Sejak awal dalam proses penyusunan PMK ini (dan turunan aturan lain dari UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan) tidak melibatkan partisipasi bermakna dari kelompok terdampak. Kementerian Kesehatan cenderung mengabaikan pengalaman hidup kelompok rentan, padahal yang diatur dalam PMK ini adalah tubuh tiap individu. Mekanisme konsultasi yang ada tidak transparan dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi organisasi penyandang disabilitas, perempuan, serta kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara substansial. Proses penyusunan aturan ini menunjukkan kegagalan Kementerian Kesehatan dalam melibatkan partisipasi bermakna masyarakat sipil. Kementerian Kesehatan nyatanya masih menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat hanya sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek dengan hak penuh untuk menentukan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Akibatnya, aturan ini tidak hanya diskriminatif tetapi juga berpotensi memperburuk ketidakadilan struktural yang sudah lama dialami oleh kelompok masyarakat.
Hilangnya Otonomi Tubuh Perempuan Disabilitas
Hari ini kami kecewa mendapati PMK No.02 Tahun 2025 masih memiliki problem kritis dalam menempatkan Orang Dengan Disabilitas. Kementerian Kesehatan terang-terangan menunjukan perspektif ableismenya melalui aturan ini. Alih-alih melindungi hak otonomi tubuh perempuan disabilitas, aturan ini justru secara gamblang menghilangkan kecakapan Orang Dengan Disabilitas terutama Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual. Melalui Pasal 62 Ayat (5) “…orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya..”. Ketentuan ini merampas hak penyandang disabilitas untuk menentukan keputusan terkait tubuhnya sendiri, termasuk dalam layanan aborsi. Mestinya daripada mencabut hak pengambilan keputusan dari Orang Dengan Disabilitas, negara seharusnya menyediakan mekanisme supportive decision-making yang memungkinkan mereka membuat keputusan dengan berbagai dukungan yang menghormati hak dan otonomi mereka, bukan malah mencabut hak tersebut.
Selain itu, penggunaan istilah “cacat” dalam regulasi ini memperkuat stigma diskriminatif. Aturan ini seharusnya berlandaskan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Sejalan dengan itu, pendekatan medical model yang menempatkan disabilitas sebagai sesuatu yang harus “diperbaiki” harus ditinggalkan, dan kebijakan kesehatan harus beralih ke human rights-based approach yang menghormati kemandirian, martabat, serta hak penuh penyandang disabilitas dalam mengambil keputusan atas hidup mereka sendiri.
Diskriminasi terhadap Orientasi Seksual dan Identitas Gender
Permenkes ini kembali menempatkan orientasi seksual sebagai disfungsi dan gangguan (Pasal 52). Ini sangat bertentangan dengan UU Kesehatan yang telah mengakui dan melindungi individu yang mengalami diskriminasi secara sosial karena orientasi seksual dan identitas gendernya. Ketentuan ini juga berlawanan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, yang secara tegas menyatakan bahwa orientasi seksual bukanlah gangguan jiwa.
Lebih dari itu, Permenkes ini secara eksplisit mempromosikan upaya-upaya korektif paksa terhadap orientasi seksual yang dianggap sebagai kelainan melalui deteksi dini (Pasal 54) dan upaya rehabilitatif (Pasal 56). Padahal, upaya korektif yang dulu dikenal dengan istilah “terapi konversi” telah dinyatakan Komite Anti Penyiksaan PBB sebagai tindak penyiksaan yang harus dihentikan. Indonesia telah berulang kali ditegur PBB dan didorong untuk mencabut kebijakan diskriminatif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Alih-alih memberikan perlindungan, Negara semakin melanggar mandat dan komitmennya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia lewat Permenkes yang menambah daftar panjang kebijakan diskriminatif. Tenaga medis yang seharusnya bebas dari tindak diskriminasi dan mengutamakan keselamatan pasien justru diberi kuasa penuh oleh Negara untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan.
Dampak dari kebijakan ini tidak bisa diabaikan. Permenkes ini jelas memperburuk terwujudnya pemenuhan hak dasar atas kesehatan fisik dan mental kelompok rentan, secara khusus kelompok LGBTIQ, yang selama ini sudah sangat kesulitan mengakses layanan kesehatan karena stigma sebagai gangguan/kelainan seksual. Upaya korektif terhadap orientasi seksual ini memenuhi unsur-unsur penyiksaan², yang diantaranya adalah menimbulkan penderitaan fisik dan mental luar biasa yang berdampak pada kehilangan keberhargaan diri dan trauma berkepanjangan; serta dilakukan untuk tujuan tertentu – berdasarkan keyakinan keliru bahwa orientasi seksual adalah gangguan sehingga upaya korektif bertujuan untuk mengembalikan martabat kemanusiaannya. Melalui Permenkes ini, unsur-unsur penyiksaan berikutnya terpenuhi, yakni Negara secara sengaja melakukan serta menyetujui upaya korektif melalui pejabat-pejabat yang berwenang, dalam hal ini tenaga medis, kesehatan, maupun institusi layanan kesehatan. Dengan memberlakukan kebijakan yang menegaskan orientasi seksual sebagai gangguan yang perlu ‘dikoreksi’, negara tidak hanya mengabaikan hak warganya tetapi juga memperkuat sistem yang menyetujui, menormalisasi serta melakukan penyiksaan.
Pembatasan Akses Layanan Aborsi
Dalam hal layanan aborsi, PMK ini berpeluang menambah pengalaman traumatis bagi korban akibat alur yang berlapis, rumit dan penuh dengan syarat administratif. Mekanisme ini mengabaikan pengalaman perempuan korban, pengalaman individu dengan kondisi darurat medis yang membutuhkan layanan aborsi untuk mengambil keputusan secara utuh. Aturan ini menyaratkan empat (4) surat yang harus diperoleh secara kumulatif untuk mengakses layanan, termasuk Surat Keterangan Penyidik (pasal 60), berpotensi menghambat korban mengakses layanan aborsi. Faktanya, tidak semua korban kekerasan seksual dan korban perkosaan dapat dan berkehendak untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. Sebagai tambahan, bahkan ketika korban memilih untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan dan membutuhkan layanan aborsi, hingga ini belum ada mekanisme internal dalam kepolisian yang dapat menerbitkan surat keterangan tersebut. Oleh karena itu, pelaporan pidana seharusnya dipisahkan dari hak individu atas keputusan prokreasi.
Layanan aborsi adalah layanan kesehatan yang menjadi bagian dari hak pemulihan kesehatan korban kekerasan seksual dan perkosaan, sebagaimana telah diatur dalam UU TPKS No.12 Tahun 2022. Tim pertimbangan yang terdiri dari lebih dari satu (1) tenaga medis juga dapat menjadi penghambat yang tidak sensitif terhadap situasi korban. Selain itu, aturan ini juga mengabaikan fakta terbatasnya tenaga medis terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Secara geografis dan ketersediaan akses, tidak semua korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan berada di wilayah dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
Dalam hal situasi darurat medis, aturan ini mengharuskan persetujuan suami dan/atau keluarga untuk mengakses layanan aborsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 62. Ketentuan ini mencabut otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri, bahkan dalam kondisi yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, persyaratan persetujuan suami atau keluarga harus dihapus demi menjamin hak perempuan atas keputusan medisnya sendiri.
Tuntutan Kami
Masyarakat Sipil telah mengajukan catatan kritis dalam proses advokasi sebelumnya terkait kebijakan ini. Namun, hingga kini, peraturan yang dikeluarkan masih belum mencerminkan perlindungan bagi kelompok rentan dan korban. Oleh karena itu, kami kembali mendesak Kementerian Kesehatan untuk menyediakan regulasi yang efektif, berperspektif korban, dan tidak diskriminatif dengan: revisi terhadap Permenkes No. 02 Tahun 2025, khususnya dalam hal berikut:
-
-
- Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan No.02 Tahun 2025 dan melakukan perubahan di antaranya:
- Menghapus semua penggolongan orientasi seksual sebagai disfungsi, kelainan, dan/atau gangguan serta upaya kuratif dan rehabilitatif yang mengikutinya;
- Menghapus Surat Keterangan Penyidik sebagai syarat administratif dalam layanan aborsi;
- Menghapus Tim Pertimbangan dalam alur akses layanan aborsi, karena prosedur ini menambah hambatan bagi korban dalam situasi darurat dan berisiko mengurangi aksesibilitas layanan;
- Menghapus persetujuan Suami dan keluarga untuk akses aborsi dalam situasi darurat medis;
- Menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa Orang Dengan Disabilitas tidak cakap mengambil keputusan, dan memastikan bahwa Individu Dengan Disabilitas berhak memberikan persetujuan sendiri tanpa harus melalui wali/tenaga medis serta mendorong penyediaan mekanisme supportive decision-making sebagai dukungan kepada Orang Dengan Disabilitas untuk membuat keputusan;
- Menghapuskan segala bentuk perlukaan termasuk penghapusan upaya-upaya simbolis dalam bagian P2GP
- Memastikan prinsip penyediaan layanan kesehatan yang inklusif, non-diskriminatif serta patuh pada standar hak asasi manusia, termasuk rekomendasi WHO dan perjanjian HAM internasional yang menegaskan bahwa orientasi seksual dan identitas gender bukan penyakit. Dalam implementasinya, sistem, budaya, dan infrastruktur layanan kesehatan harus mengakomodasi kebutuhan LGBTIQ dengan cara yang bermartabat dan inklusif, serta melindungi kelompok LGBTIQ dari praktik berbahaya seperti diskriminasi, penyiksaan berbentuk upaya korektif, dan kekerasan berbasis SOGIESC.
- Melakukan perluasan akses dan metode aborsi (tidak terbatas pada metode prosedural, tetapi juga medikamentosa) di dalam kerangka task shifting untuk memastikan keterlibatan profesi lain seperti bidan, apoteker, paramedis, sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 dan mengacu pada panduan termutakhir WHO terkait aborsi. Adanya perluasan akses dan metode ini adalah cara untuk memastikan tata laksana aborsi aman dapat diberikan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat primer dan mengakomodir situasi keterbatasan layanan.
- Melibatkan masyarakat sipil dalam proses monitoring dan evaluasi. Untuk menjamin bahwa masyarakat sipil, khususnya kelompok advokasi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok LGBTIQ, terlibat secara aktif dalam pemantauan implementasi regulasi kesehatan yang menyangkut hak dan perlindungan mereka. Sekaligus mendorong penyedia layanan kesehatan untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan korban kekerasan seksual, tanpa stigma atau diskriminasi.
- Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan No.02 Tahun 2025 dan melakukan perubahan di antaranya:
-
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan Adil dan Inklusi
-
-
- Save All Women and Girls (SAWG)
- Yayasan Kesehatan Perempuan
- Perhimpunan Jiwa Sehat
- Samsara
- Asosiasi LBH APIK Indonesia
- Arus Pelangi
- Qbukatabu
- Institute for Criminal Justice Reform
- PKBI Yogyakarta
- Front Anti Kekerasan Maluku Utara
- Woi Sulawesi Utara
- Gerak 28 September
- Transmen Indonesia
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Marsinah.id
- Alemu
- LBH Masyarakat
- Amerta Raksa Kayana
- Komunitas Perempuan Bumi
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
- SIGAB Indonesia
- Diksi Foundation
- HWDI – Sulawesi Selatan
- Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo
- Jakarta Feminist
- Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
- Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)
- OHANA
- CIQAL
- SAPDA
- Feminis Themis
- PPDI Kalimantan Timur
-
¹https://lbhapik.or.id/siaran-pers-masyarakat-sipil-mendesak-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-yang-inklusif-adil-dan-setara-dalam-seluruh-proses-penyusunan-kebijakan-turunan-uu-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/
²Berdasarkan Pasal 1 UU. No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia