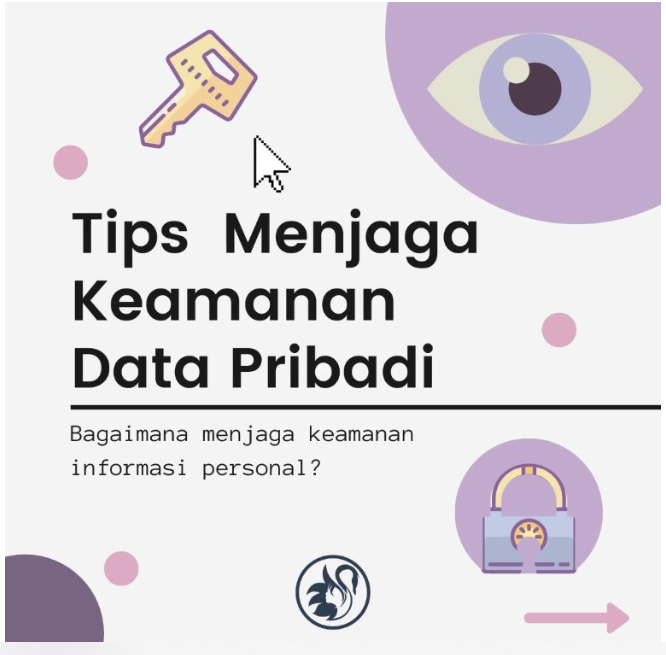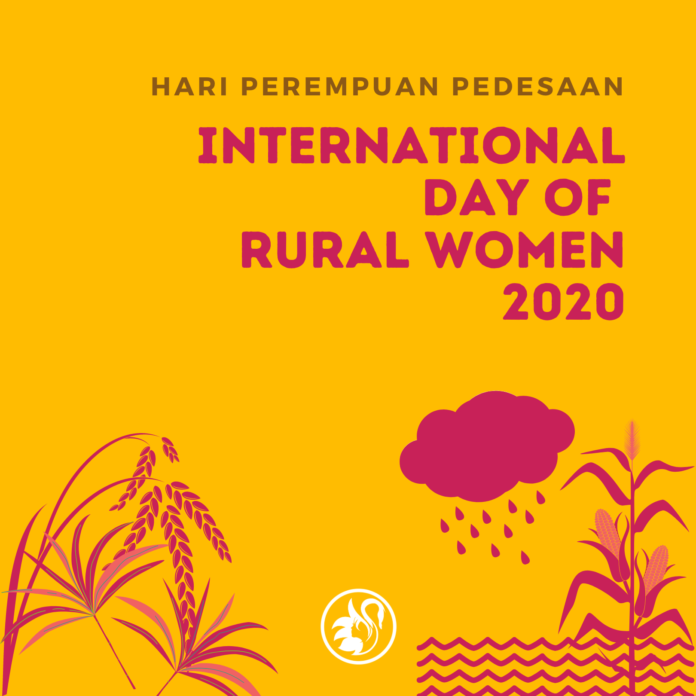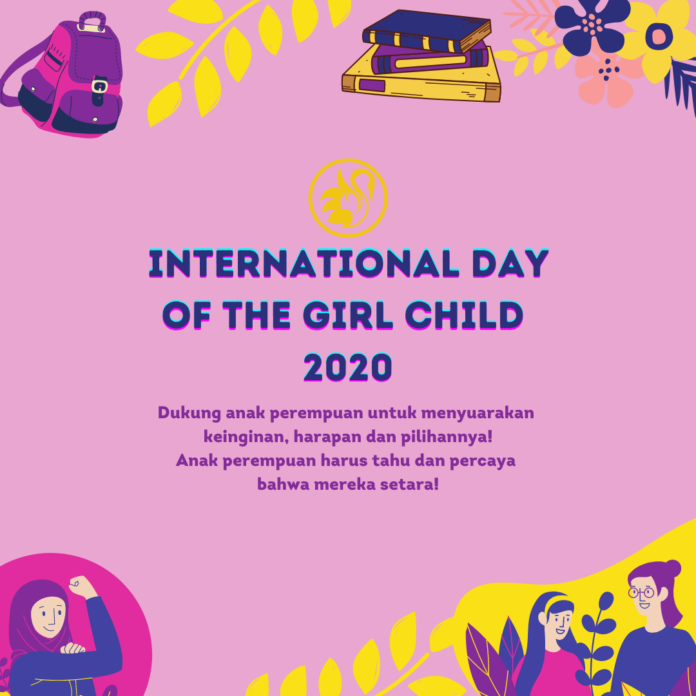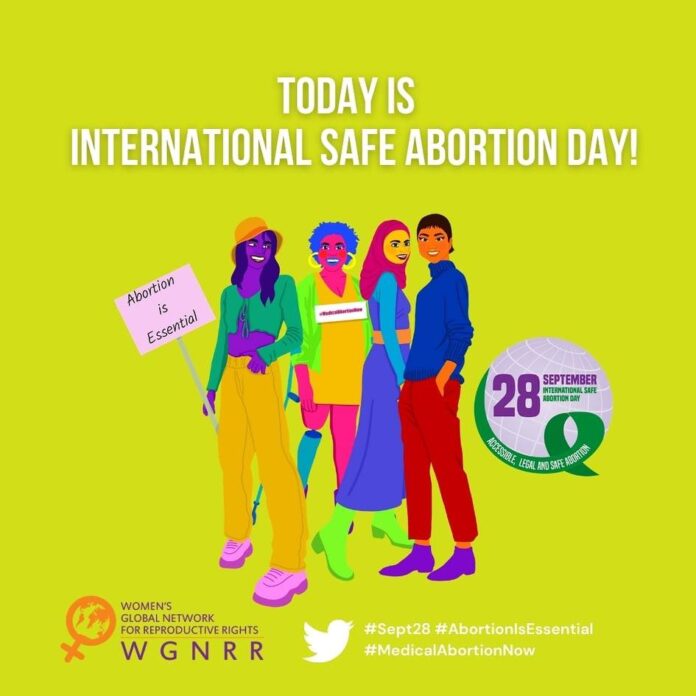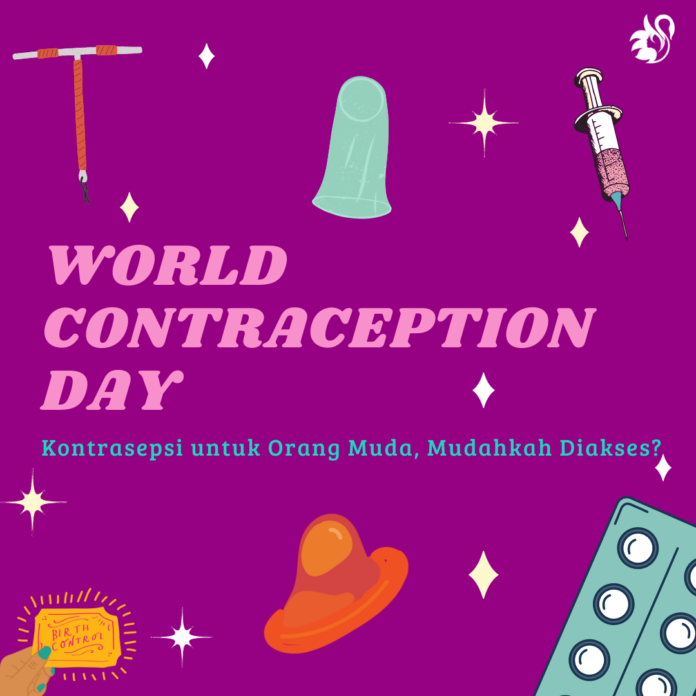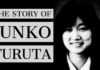Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia[1]
The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family
Jakarta, 19 October 2020
Kami, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, hendak memberikan respon sehubungan dengan adanya peredaran draf dan non-paper mengenai “The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family” (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Deklarasi”). Deklarasi ini didukung oleh sebagian kecil negara anggota PBB, termasuk Pemerintah Indonesia sebagai co-sponsor, dimana deklarasi ini memberikan kesan akan menjamin penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik kepada perempuan dan anak perempuan dalam skala global.
Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas akuntabilitasnya yang selama ini sangat konsisten dalam melibatkan masyarakat sipil melalui konsultasi dalam pengambilan keputusan dalam sejumlah komitmen dan perjanjian internasional. Namun, kami melihat bahwa dalam pengambilan keputusan mengenai Deklarasi ini, pelibatan dan konsultasi dengan masyarakat sipil tidak terjadi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pada Deklarasi yang menitikberatkan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan ditentukan tanpa diberikannya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mengerti dan mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan mereka.
Kelompok organisasi masyarakat sipil yang bekerja di beragam lintas sektor isu sosial sangat mengkhawatirkan tujuan dari Deklarasi ini. Kami melihat bahwa tujuan dari Deklarasi ini adalah untuk menetapkan dan mementingkan pengistimewaan hirarki akan hak yang salah, yang mengesampingkan hak asasi manusia yang universal, saling ketergantungan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan mengesampingkan hak lain yang seharusnya tidak dapat dicabut. Dalam konteks negara Indonesia, kita secara khusus melihat bahwa akan ada dampak negatif yang sangat signifikan yang akan mencederai dan mengganggu kesejahteraan dan kehidupan perempuan, anak perempuan dan keluarga. Hal ini bertentangan dengan usaha dan keberhasilan kita selama ini dalam memajukan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang merupakan hak asasi manusia yang universal bagi setiap orang.
Pernyataan Kami
Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk meneruskan komitmennya terhadap pendirian prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / Universal Declaration of Human Rights (UDHR), juga dalam Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Prinsip-prinsip tersebut telah memberikan organisasi masyarakat sipil kerangka yang normatif, sesuai dengan hukum dan secara etis untuk terus memastikan penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia. Kami turut mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kebijakan lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW.
“The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family” secara jelas mengecualikan hak dan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya untuk perempuan dan anak perempuan. Ini tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di Indonesia maupun dengan tujuan secara internasional untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, yang sudah dibangun bersama-sama selama puluhan tahun ini.
Secara khusus, kami ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu:
- Prinsip bahwa semua hak adalah sama merupakan produk dari ketergantungan hak asasi manusia: penyangkalan salah satu hak sejatinya akan menghalangi pemenuhan hak lainnya. Deklarasi ini tidak merujuk pada CEDAW, kebijakan internasional yang mengatur Hak Perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984.[2] Kami percaya bahwa ada kemungkinan besar bahwa Deklarasi ini memiliki tujuan untuk mengganggu tercapainya keadilan bagi perempuan melalui pemusnahan segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender.
- Deklarasi menyebutkan bahwa “jaminan kesehatan universal adalah mendasar untuk tercapainya Sustainable Development Goals terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan,”[3] dilanjutkan dengan “kesehatan adalah suatu keadaan yang lengkap dan sejahtera secara fisik, mental dan sosial dan tidak semata tiadanya penyakit atau kesakitan”[4] dan “kebanyakan fokus dasi sistem pelayanan kesehatan adalah untuk mengobati kesakitan dibandingkan dengan upaya holistik untuk menjaga kesehatan yang optimal dan pencegahan.”[5] Hak untuk hidup, yang dianggap sebagai hak politik, tergantung pada hak terhadap akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan universal, hak ekonomi. Pelayanan kesehatan harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya diskriminasi berbasis tingkat kemiskinan, agama, ras, etnis, gender, identitas dan orientasi seksual, afiliasi politik, atau status imigrasi. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan khususnya hak atas kesehatan seksual dan reproduksi dan otonomi tubuh.[6]
- Pelayanan Kesehatan mencakup layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan akses kepada aborsi aman. Deklarasi ini gagal membuktikan argumentasinya tentang tidak adanya “… hak internasional terhadap aborsi, atau kewajiban internasional apapun kepada negara untuk membiayai ataupun memfasilitasi aborsi, yang konsisten dengan konsensus internasional yang mengikat yang menyatakan bahwa negara mempunyai hak atas kedaulatan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang selaras dengan undang-undang dan kebijakan masing-masing.” Pada kenyataannya rekomendasi umum (general recommendation) CEDAW No. 24: Artikel 12 tentang Konvensi perempuan dan kesehatan menyebutkan “Aborsi yang tidak aman adalah penyebab utama dari kesakitan dan kematian ibu. Oleh karenanya, negara anggota seharusnya melegalisasi aborsi setidaknya dalam kasus perkosaan, inses, ancaman atas nyawa dan/atau kesehatan ibu, atau adanya gangguan yang parah pada janin, serta memberikan akses kepada perempuan kepada layanan pasca aborsi yang berkualitas, terutama dalam kasus komplikasi yang menyebabkan adanya aborsi tidak aman. Negara anggota seharusnya juga menghilangkan penghukuman kepada perempuan yang melakukan aborsi.” Senada dengan itu, tanggapan Komite Hak Anak No. 20(2016) tentang implementasi hak-hak anak pada masa remaja mendesak pemerintah untuk tidak mengkriminalisasi segala bentuk aborsi dan menghilangkan hambatan kepada aksesnya. Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Komite Penghapusan Penyiksaan juga telah menyerukan penghapusan hukuman atas aborsi dan pelaksanaan upaya-upaya untuk memastikan akses kepada aborsi yang aman dan legal.[7]
- CEDAW Artikel 4 menyatakan bahwa “Negara seharusnya mengecam kekerasan terhadap perempuan dan seharusnya tidak menggunakan adat istiadat, tradisi atau pertimbangan keagamaan untuk menghindarkan diri dari kewajibannya untuk menghapuskan kekerasan. Negara seharusnya segera mengambil semua langkah yang diperlukan untuk adanya kebijakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.” Setiap tahunnya diperkirakan ada 25 juta aborsi tidak aman yang terjadi. Antara 5% dan 13% kematian ibu disebabkan oleh aborsi yang disengaja, sebagian besar dari praktek yang tidak aman, dimana setiap tahunnya merenggut nyawa 44.000 perempuan dewasa dan remaja.[8]. Sebuah studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tentang dampak COVID-19 terhadap perempuan di Indonesia melaporkan peningkatan angka kekerasan domestik selama wabah. Kekerasan seksual dilaporkan sebagai kasus kedua yang tertinggi setelah kasus kekerasan fisik.[9] Ini mengindikasikan adanya kebutuhan berkelanjutan dan bahkan semakin tinggi untuk adanya layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, legal dan dapat diakses oleh perempuan dewasa dan remaja di Indonesia.[10]
- Kami memuji disahkannya Peraturan Pemerintah no. 61/2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 3/2016 untuk menanggapi rekomendasi CEDAW yang disebutkan di atas. Keduanya sangat sesuai dengan perspektif fiqih kritis yang menjamin aborsi.[11] Oleh karenanya, ada kebutuhan mendesak untuk menggeser dan menata ulang pendekatan praktis yang digunakan oleh negara untuk mengelola aborsi aman, tidak hanya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) tetapi juga untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual terlindungi dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
- Kami menghargai perhatian kepada keluarga sebagai unit terkecil yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian, ada banyak bentuk keluarga dan terdiri dari individu-individu dengan persoalan dan kebutuhan yang berbeda-beda.[12] Penekanan yang diberikan oleh Deklarasi ini kepada keluarga adalah upaya yang sistemik dan terstruktur untuk mengabaikan kesetaraan gender dengan membatasi ruang dan peran perempuan dengan dalih kepentingan terbaik untuk keluarga. UN Women (2019) mencatat bahwa retorika global tentang ‘nilai-nilai keluarga’ adalah representasi dari upaya terukur oleh pihak-pihak yang mengindahkan hak perempuan untuk membuat keputusan atas dirinya untuk memundurkan capaian kesetaraan gender selama beberapa dekade.[13] Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menekankan penggunaan definisi luas dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang melampaui struktur fisik dan gender. Sebuah keluarga harus didefinisikan sebagai sebuah unit dimana asuhan dan perlindungan fisik dan emosional yang konsisten saling diberikan dan dijaga. Tujuan Deklarasi untuk melindungi keluarga akan sia-sia kecuali jika negara menjamin akses tanpa diskriminasi bagi seluruh keluarga atas kesehatan, kebutuhan dasar lainnya, mata pencaharian, dan tidak mempromosikan domestikasi ibu dan perempuan.
Pemerintah Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia terikat kepada kewajiban untuk memenuhi standar yang perjanjian-perjanjian tersebut. Kami, Koalisi Untuk Hak Seksual dan Kesehatan reproduksi mendesak Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri untuk membatalkan penandatanganan ‘The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family’ seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Deklarasi ini tidak hanya inkonstitusional berdasarkan undang-undang di Indonesia tetapi juga tidak selaras dengan tujuan Pemerintah Indonesia untuk pencapaian SDGs. Terutama, Deklarasi ini berbahaya bagi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan keluarga di Indonesia.
Dukungan terhadap pernyataan sikap dari masyarakat sipil di Indonesia terhadap Deklarasi Konsensus Jenewa:
Organisasi:
- Aliansi Satu Visi (ASV)
- AMAN Indonesia
- CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)
- CIQAL
- Dialoka
- GERAK Perempuan
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
- Institute for Women’s Empowerment
- Institute of Criminal Justice Reform (ICJR)
- Institut Perempuan
- Jaringan Akademisi Gerak Perempuan
- Kalyanamitra
- KePPak Perempuan
- KITASAMA
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Konde Institute
- LBH Apik Jakarta
- OHANA
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
- Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
- Rahima
- Rutgers WPF Indonesia
- Samsara
- Save All Women and Girls (SAWG)
- Solidaritas Perempuan
- Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP UI
- Yayasan Amalshakira
- Yayasan IPAS Indonesia
- YAPESDI
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
Perseorangan:
- Atas Hendartini Habsjah
- Dewi Tjakrawinata
- Diana Pakasi
- Dinda Nuurannisaa Yura
- Donna Swita
- Fatimah Az-Zahro
- Frenia Nababan
- Hanifah Haris
- Ika Ayu
- Irwan Hidayana
- Kencana Indrishwari
- Listyowati
- Luviana
- Marcia Soumokil
- Mike Verawati
- Nanda Dwinta
- Nuning
- Pera Soparianti
- Rena Herdiyani
- Reni Kartikawati
- Revita
- Risna
- Shera Rindra Mayang Putri
- Siti Mazuma
- Valentina Sagala
[1] The Indonesian Coalition for Sexual and Reproductive Health
[2] Indonesia had passed the convention into law on July 24, 1984.
[3] United Nations General Assembly. (2019). “Political declaration of the high-level meeting on universal health coverage” (Paragraph 5). New York.
[4] International Health Conference. (1946). “Constitution of the World Health Organization.” New York.
[5] Assembly, U. G. (2000). Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform for Action. UN doc., S-23/3, 12 (Paragraph 11). New York.
[6] In the Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017), Indonesia has stated its support for the recommendation to “adopt legislative and policy measures to ensure women and adolescents have access to sexual education and free and friendly reproductive health services” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.27). Furthermore, GOI has stated its support for the recommendation to ensure all of Indonesia’s laws and regulations “are consistent with its human rights obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and CEDAW, as well as improving coordination among responsible agencies and ministries” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.104). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[7] Human Rights Watch. (2017). Human Rights Law and Access to Abortion.
[8] https://www.rcog.org.uk/leadingsafechoices
[9] Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Perubahan Dinamika Rumah Tangga dalam Masa Pandemi Covid-19 [Press Release on the National Commission on Violence Against Women regarding the Changes of Household Dynamics during the COVID-19 Pandemic], 3 June, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news- siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020, accessed on 19 October 2020.
[10] During the Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017), Indonesia has stated its support for the recommendation to “redouble efforts in sex education and access to sexual and reproductive health in the whole country with a view to reducing maternal mortality and combating AIDS, early pregnancies, abortions carried out in situations of risk, child marriages and violence and sexual exploitation” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.91). In addition, GOI has stated its support for the recommendation to adapt legislative frameworks so that married and unmarried women and girls can gain access to (A/HRC/36/7/Add. 1, Para. 10, Rec. 141.32) and information about sexual and reproductive health services (Rec. 141.65). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[11] Ulfah, A. M. (2006). Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan [The Fiqh on Abortion: Narratives of Strengthening Women’s Reproductive Rights]. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
[12] The Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017) has witnessed Indonesia’s support for the recommendation to “Guarantee access to contraception irrespective of marital status and repeal all laws which restrict women’s and girls’ access to sexual and reproductive health information” (A/HRC/36/7/Add. 1, Para. 10, Rec. 141.64); and “eliminate legal and political restrictions that discriminate against women on the basis of their personal status, and those that may violate their sexual and reproductive rights” (Rec. 141.67). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[13] UN Women. (2019). Progress of the World’s Women 2019–2020: Families in a Changing World. New York: United Nations.
ENGLISH VERSION
Statement of Indonesian CSOs[1]
The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family
Jakarta, 19 October 2020
In light of the recently circulated draft and non-paper on “The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family” (hereafter referred to as “the Declaration”), Indonesian NGOs wish to respond. The Declaration is supported by a small group of UN member states, including the Government of Indonesia (GOI) as a co-sponsor, and gives the impression that it will provide women and girls around the globe with better healthcare.
In the past, we have always commended GOI for its consistent engagement and consultation with the civil society on deliberating decisions on a number of international commitments and treaties. Thus it is concerning to learn that this has not been the case for this particular declaration. Women and girls have been put at the core of the Declaration yet have not been invited to understand and dissect the consequences it will have on our lives.
The civil society groups that work on various social issues in Indonesia are gravely concerned about the intent of the declaration. The Declaration seeks to establish and advance a false and preferential hierarchy of rights, ignores the basic human rights tenets of universality, interdependency, and indivisibility, and distills the range of unalienable rights. In the context of Indonesia, we particularly foresee that there will be significant negative implications that will hamper and disrupt the wellbeing and lives of women, girls, and families. This goes against our achievements and determination thus far in advancing access to quality healthcare, which is a basic universal human right for every individual.
Our statement
We are asking for GOI’s continued commitment to the founding human rights principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), as well as in the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). These principles continue to provide civil society organizations with a crucial legal and normative framework for ensuring the human rights and well-being of all people in Indonesia and around the world. We remind GOI that Indonesia has also ratified its own laws on human rights, including Law no. 39/1999 on Human Rights and Law no. 7/1984 on CEDAW.
“The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family” explicitly excludes sexual and reproductive health and rights services that are unique to women and girls. This does not align with Indonesia’s laws nor with the international determination to improve women’s access to healthcare, built collectively over many decades.
Specifically, we would like to make the following points:
- The principle that all rights are equal is a product of the indivisibility of human rights: the denial of one right necessarily impedes the enjoyment of other rights. The Declaration does not cite CEDAW, the international bill of rights for women, ratified by GOI in 1984.[2] We believe it is highly likely that the Declaration intends to violate substantive equality for women through elimination of all forms of discrimination based on gender prejudice.
- The Declaration states that “universal health coverage is fundamental for achieving the Sustainable Development Goals related not only to health and well-being,”[3] with further recognition that “health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”[4] and that “the predominant focus of health-care systems on treating illness rather than maintaining optimal health also prevents a holistic approach.”[5] The right to life, considered a political right, depends on the right to universal access to affordable healthcare, an economic right. Healthcare must be provided to all who need it, without discrimination on the basis of wealth, religion, race, ethnicity, gender, sexual identity and orientation, political affiliation, or immigration status. Therefore, GOI has obligations to respect, protect, and fulfill human rights, including women’s rights and specifically rights regarding sexual and reproductive health and bodily autonomy.[6]
- Healthcare includes comprehensive reproductive healthcare and access to safe abortion services. The Declaration fails to demonstrate its argument on the absence of “… international right to abortion, nor any international obligation on the part of the States to finance or facilitate abortion, consistent with the long-standing international consensus that each nation has the sovereign right to implement program and activities consistent with their laws and policies.” This is despite the fact that CEDAW general recommendation No. 24: Article 12 of the Convention on women and health states that “Unsafe abortion is a leading cause of maternal mortality and morbidity. As such, States parties should legalize abortion at least in cases of rape, incest, threats to the life and/or health of the mother, or severe fetal impairment, as well as provide women with access to quality post-abortion care, especially in cases of complications resulting from unsafe abortions. States parties should also remove punitive measures for women who undergo abortion.” Similarly, the Committee on the Rights of the Child has urged governments to decriminalize abortions in all circumstances and remove barriers to access. The UN Human Rights Committee, the Committee on Economic Social and Cultural Rights, and the Committee against Torture have also called removal of penalties for abortion and for the implementation of measures to ensure safe, legal access to abortion.[7]
- CEDAW Article 4 states that “States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination. States should pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating violence against women.” Every year, an estimated 25 million unsafe abortions take place. Between 5% and 13% of maternal deaths are attributed to induced abortion, mostly all unsafe procedures, with an annual death toll up to 44,000 women and girls[8]. A recent survey by the Indonesian Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) on the impact of COVID-19 on women in Indonesia reported an increased number of domestic violence during the pandemic, with sexual violence being the second-most reported form of violence following physical violence.[9] This indicates an ongoing and even expanding need for safe, legal and accessible sexual and reproductive health services for Indonesia’s women and girls.[10]
- We commend the enactment of Government Regulation no. 61/2014 and Ministry of Health Decree no. 3/2016 in response to the above CEDAW general recommendation. These are inline with critical perspectives that fiqh guarantees abortion.[11] Hence, there is an urgent need to shift and reconstruct the country’s in-practice approach to managing safe abortion in order to not only reduce Indonesia’ maternal mortality rate but also ensure victims of sexual violence are protected and receive the help they need.
- We appreciate the attention to the family as the smallest unit influencing the health and wellbeing of its members. Nevertheless, families take different forms, and consist of different individuals with different issues and needs.[12] The Declaration’s heavy emphasis on the family is a systematic and structured exercise to neglect gender equality through limiting the space for and role of women under the guise of promoting the best interest of the family. UN Women (2019) writes that the global rhetoric of ‘family values’ represents a concerted effort to roll back many decades of gender equality achievements by those who deny women the right to make their own decisions.[13]
The Government of Indonesia is a signatory to numerous international human rights agreements and is therefore bound to comply with the standards set by those agreements. We, the Indonesian Coalition for Sexual and Reproductive Health, strongly urge the Government of Indonesia, in particular the Department of Foreign Affairs, to cancel the signing of “The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family” as proposed by the United States. The Declaration is not only unconstitutional by Indonesian laws and out of alignment with the stated intention of the Government of Indonesia towards achieving the SDGs, but will also certainly be disastrous for the sexual and reproductive health of Indonesian women and families.
[1] The Indonesian Coalition for Sexual and Reproductive Health
[2] Indonesia had passed the convention into law on July 24, 1984.
[3] United Nations General Assembly. (2019). “Political declaration of the high-level meeting on universal health coverage” (Paragraph 5). New York.
[4] International Health Conference. (1946). “Constitution of the World Health Organization.” New York.
[5] Assembly, U. G. (2000). Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform for Action. UN doc., S-23/3, 12 (Paragraph 11). New York.
[6] In the Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017), Indonesia has stated its support for the recommendation to “adopt legislative and policy measures to ensure women and adolescents have access to sexual education and free and friendly reproductive health services” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.27). Furthermore, GOI has stated its support for the recommendation to ensure all of Indonesia’s laws and regulations “are consistent with its human rights obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and CEDAW, as well as improving coordination among responsible agencies and ministries” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.104). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[7] Human Rights Watch. (2017). Human Rights Law and Access to Abortion.
[8] https://www.rcog.org.uk/leadingsafechoices
[9] Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Perubahan Dinamika Rumah Tangga dalam Masa Pandemi Covid-19 [Press Release on the National Commission on Violence Against Women regarding the Changes of Household Dynamics during the COVID-19 Pandemic], 3 June, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news- siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020, accessed on 19 October 2020.
[10] During the Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017), Indonesia has stated its support for the recommendation to “redouble efforts in sex education and access to sexual and reproductive health in the whole country with a view to reducing maternal mortality and combating AIDS, early pregnancies, abortions carried out in situations of risk, child marriages and violence and sexual exploitation” (A/HRC/36/7, Paragraph 139, Rec. 139.91). In addition, GOI has stated its support for the recommendation to adapt legislative frameworks so that married and unmarried women and girls can gain access to (A/HRC/36/7/Add. 1, Para. 10, Rec. 141.32) and information about sexual and reproductive health services (Rec. 141.65). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[11] Ulfah, A. M. (2006). Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan [The Fiqh on Abortion: Narratives of Strengthening Women’s Reproductive Rights]. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
[12] The Third Cycle of the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review (2017) has witnessed Indonesia’s support for the recommendation to “Guarantee access to contraception irrespective of marital status and repeal all laws which restrict women’s and girls’ access to sexual and reproductive health information” (A/HRC/36/7/Add. 1, Para. 10, Rec. 141.64); and “eliminate legal and political restrictions that discriminate against women on the basis of their personal status, and those that may violate their sexual and reproductive rights” (Rec. 141.67). See further details via https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ UPR/Pages/IDIndex.aspx, accessed on 19 October 2020.
[13] UN Women. (2019). Progress of the World’s Women 2019–2020: Families in a Changing World. New York: United Nations.