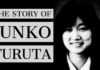Menurut The Body Project yang dikembangkan oleh Program Studi Perempuan Universitas Bradley, Illinois, standar kecantikan adalah arbitrer dan sangat berbeda dari budaya satu dengan budaya lainnya. Begitu juga halnya di Indonesia. Standar kecantikan berubah secara bertahap dari waktu ke waktu. Nilai-nilai kecantikan tradisional sedang berubah sebab pengaruh media, industri kosmetik dan iklan mereka. Di industri kecantikan Indonesia sendiri, salah satu produk paling populer dengan pendapatan tertinggi adalah produk pemutih kulit. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak permintaan dari pasar Indonesia yang menginginkan kulit lebih cerah. Di antara para perempuan di Indonesia, kulit yang lebih cerah lebih diinginkan dibandingkan dengan yang lebih gelap. Sayangnya, banyak dari perempuan itu tidak tahu bahwa kulit gelap mereka secara ilmiah bermanfaat untuk hidup di negara tropis seperti Indonesia.
Kembali pada abad ke 10 ketika candi seperti Prambanan dibangun (UNESCO), standar kecantikan di Indonesia tidak terlalu fokus pada warna kulit, melainkan fokus pada kesuburan. Kecantikan didefinisikan oleh proporsi tubuh. Relief dan ukiran di Prambanan dan juga Borobudur menggambarkan perempuan dengan sosok melengkung yang melambangkan kesuburan, yang pada saat itu dianggap sebagai perempuan cantik. Contoh lain dari proporsi tubuh mendefinisikan standar kecantikan yang terjadi di suku Dayak, telinga panjang dianggap sebagai cantik.
Seiring berjalannya waktu, standar kecantikan secara bertahap berubah. Saat ini di suku Dayak, generasi yang lebih muda kurang menganggap telinga panjang sebagai standar kecantikan yang signifikan. Selanjutnya, seiring globalisasi yang terjadi di Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek seperti media dan hiburan, standar kecantikan juga berubah. Seperti yang sering muncul di televisi, gaya aktris telah menjadi standar kecantikan baru.
Sekitar tahun 70-an dan 80-an di Indonesia, aktris seperti Christine Hakim, Lidya Kandou, dan Marissa Haque mewakili lambang ras campuran kecantikan di era itu. Sekitar tahun 90an, sinetron menjadi sangat populer, beserta program dan iklan didominasi oleh aktris Eurasia seperti Tamara Bleszinsky yang keturunan Polandia-Indonesia. Pada tahun 2000-an lebih banyak bintang Asia seperti Leony, Agnes Monica, dan Laura Basuki naik di pasaran. Dan tren kecantikan terbaru yang dimulai dari 2010 saat sinetron, musik dan fashion Korea menjadi populer di Indonesia, ikon selebriti Korea dengan kulit putih dan gigi putih sempurna menjadi populer (Jakarta Post 2014). Semua orang menginginkan kulit yang cerah, yang meningkatkan permintaan produk pemutih kulit.
Produk pemutih kulit menempati peringkat tertinggi di antara semua produk dalam industri kosmetik di Indonesia. Iklan pemutih kulit mendominasi lanskap majalah wanita Indonesia. Dalam penelitian L. Ayu Saraswati, Cosmopolitan Whiteness: The Effects and Affects of Skin Whitening Advertisements in a Transnational Women’s Magazine in Indonesia, Saraswati berfokus pada efek iklan produk pemutih di majalah populer, Cosmopolitan, di Indonesia. Di majalah tersebut, krim pemutih model Kaukasia menjadi tren. Kemunculan iklan ini menimbulkan pertanyaan; apa jenis standar kecantikan yang majalah suguhkan pada perempuan Indonesia? Model Kaukasia tentu saja tidak mewakili pasar di mana tempat produk dijual. Secara genetik, mereka tidak memiliki DNA kulit yang sama dengan kulit yang dimiliki perempuan Indonesia. Selain itu, iklan semacam ini juga mengirimkan pesan keliru terhadap perempuan Indonesia, dengan menyarankan perempuan untuk memiliki warna kulit tertentu yang secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilikinya.
Ketika produsen pemutih kulit memasarkan produk, iklan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini menggunakan sebagian besar konotasi negatif untuk kulit yang lebih gelap. Produk kecantikan lokal seperti Pond biasa memasarkan produk dengan tagline “Pond’s White Detox “. Penamaan produk khusus ini menawarkan ide ke seluruh khalayak Indonesia, terutama perempuan, bahwa kulit yang tidak putih atau kulit yang lebih gelap adalah “beracun” yang perlu “didetoksifikasi”.
Iklan lain dari Pond’s juga mengatakan ““Dark out, White In. Increase your face value ”. Jenis iklan ini menurunkan derajat wanita Indonesia dengan kulit yang lebih gelap melalui pemilihan kata-kata tertentu “Tingkatkan nilai wajah Anda” yang menunjukkan bahwa orang lebih berharga ketika mereka memiliki kulit lebih putih. Perusahaan-perusahaan iklan hanya menggunakan perempuan “cantik” yang menghasilkan efek positif terhadap perempuan dengan warna kulit yang cerah. Ini kemudian akan mengarah ke audiens dari iklan-iklan yang mempersepsikan ide tersebut bahwa warna kulit yang lebih putih lebih cantik. Selain itu, mereka juga membantu memperkuat hubungan kekuasaan di mana yang putih memegang posisi tertinggi. Iklan ini merekonstruksi wajah berkulit putih sebagai sosok cantik, sosok yang diinginkan, dan menghasilkan efek positif.
Seorang sarjana studi budaya feminis, Sara Ahmed berpendapat, “Beberapa objek lebih dari yang lain mewujudkan janji kebahagiaan. Dengan kata lain, kebahagiaan mengarahkan kita pada objek-objek tertentu, seolah-olah objek-objek tersebut dibutuhkan untuk kehidupan yang baik ”(Ahmed 2007). Sehubungan dengan penelitian ini produk pemutih kulit ataupun iklan menjadi objek yang diperlukan untuk kehidupan yang baik. Fakta khusus tersebut menyebabkan perempuan Indonesia menggunakan semua jenis metode untuk meningkatkan kemulusan kulit mereka, termasuk penggunaan produk yang sebenarnya ada dalam daftar produk pemutihan ilegal yang diterbitkan oleh BPOM, sebuah badan Indonesia yang mengatur distribusi makanan dan obat-obatan. Produk ilegal tersebut mungkin mengandung jumlah merkuri yang lebih tinggi. Merkuri menyebabkan bintik-bintik hitam, iritasi kulit, dan dosis tinggi dapat menyebabkan gejala yang sama berbahaya seperti kerusakan otak dan ginjal (Saraswati 2012). Merkuri juga merupakan salah satu unsur karsinogenik yang dapat memicu kanker. Fakta ini tentu saja bertentangan dengan iklan pemutihan kulit sebagai objek yang diperlukan untuk kehidupan yang baik.
Fakta bahwa perempuan masih membeli produk pemutih yang berbahaya diperkuat oleh diskusi media yang berlangsung di RSU Bunda Jakarta, 15 Januari 2016, dimana onkolog Afrimal Syafarudin menyatakan, “Salah satu dari pasien saya menderita kanker sebagai akibat dari penggunaan kosmetik. Dalam pengamatan saya, mereka menggunakan krim pemutih yang menghasilkan kulit lebih putih hanya dalam dua atau tiga hari ”. Ahli lain, dokter kulit Rachel Djuanda mengatakan, tidak ada yang namanya krim pemutih kulit, yang ada hanyalah krim memutihkan kulit. Rachel juga menyarankan agar orang harus ekstra hati-hati terhadap produk yang langsung menyentuh kulit mereka (Kompas 2016).
Selain produk dan media yang mewujudkan pendapat warna kulit yang lebih putih ialah lebih cantik daripada warna kulit yang lebih gelap, para perempuan sendiri juga meremehkan satu sama lain karena memiliki warna kulit yang lebih gelap. Ketika wanita Indonesia terlibat dalam percakapan, selain ‘Ya Tuhan! Kamu kok jadi gemuk? ’ yang menggerakkan negativitas tubuh, pertanyaan” Oh my god! Apa kulitmu jadi lebih gelap? ’adalah salah satu pertanyaan yang paling sering didengar. Percakapan ini menggambarkan bagaimana masyarakat lebih suka ketika perempuan memiliki kulit yang lebih putih dan perempuan lain merasa enggan dan mempunyai persepsi buruk pada dirinya ketika mereka memiliki kulit yang lebih gelap. Kulit yang lebih gelap dianggap sangat negatif.
Dorongan untuk menggunakan produk pemutih agar memenuhi standar masyarakat di antara para perempuan Indonesia saat ini dimulai ketika mereka remaja. Remaja di masa puber mereka merasakan perubahan dan kematangan yang datang melalui tubuh mereka. Periode kehidupan ini sangat penting bagi remaja tersebut, karena sebagian besar perubahan terjadi baik secara fisik maupun secara permanen pada periode ini. Pada periode remaja juga, mereka mulai mewujudkan nilai khusus seperti, ‘kulit putih lebih unggul dari kulit yang lebih gelap’. Penilaian seperti ini adalah proses berpikir yang sangat berbahaya. Hal ini dapat merusak dan mengganggu mereka sepanjang kehidupan dewasa .
Tidak dapat dipungkiri bahwa kulit yang lebih gelap membuat sebagian besar perempuan Indonesia merasa tidak nyaman dan malu. Namun, perempuan juga malu mengakui menggunakan produk kulit pemutih. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan L. Ayu Saraswati untuk penelitiannya, “Malu: Coloring Shame and Shaming the Color of Beauty in Transnational Indonesia”. Seorang yang diwawancara mengakui bahwa ketika dia di sekolah menengah, teman-temannya akan bertanya apakah dia menggunakan riasan atau tidak. Dia tidak akan berani mengaku menggunakan makeup untuk menutupi fakta bahwa kulitnya gelap. Selain itu, perempuan yang diwawancarai dalam penelitian Saraswati sering diabaikan karena tidak memiliki kulit yang lebih terang yang merupakan parameter untuk dianggap sebagai sosok yang cantik (Saraswati 2012).
Para perempuan takut dipermalukan ketika mereka tidak memiliki kulit yang lebih terang. Berdasarkan wawancara langsung, hampir semua perempuan dengan warna kulit yang lebih gelap dianggap tidak diinginkan oleh pria Indonesia. Sebaliknya, perempuan Indonesia sering digambarkan sebagai menarik oleh orang asing karena sifat alami mereka yang dimiliki, seperti kulit yang lebih gelap, mata gelap dan rambut gelap. Lebih banyak perempuan Indonesia yang harus melihat diri mereka dengan cara yang positif seperti itu.
Sangat disayangkan bahwa sebagian besar wanita Indonesia tampaknya mengabaikan fakta bahwa memiliki kulit yang lebih gelap sangat bermanfaat ketika tinggal di negara tropis. Dengan kulit yang lebih gelap, perempuan Indonesia terlindung dari intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, kulit gelap juga merupakan perisai alami yang melindungi dari penyakit kulit berbahaya dan menetralkan efek berbahaya yang disebabkan oleh radiasi kimia yang merusak (Jablonski dan Chaplin 2000).
Bio-antropologi yang mempelajari tentang variasi warna kulit di lima benua dengan jelas menyatakan bahwa intensitas yang lebih tinggi dan lebih lama terkena paparan sinar matahari menghasilkan warna kulit yang lebih gelap karena jumlah melanin yang diproduksi lebih tinggi. Melanin mencegah UV melewati kulit sampai ke batas di mana vitamin D yang disintesis oleh UV, berarti kulit yang lebih gelap dapat membantu mencegah kelebihan hypervitamonis dan asam folat (Indriati 2005). Kulit yang lebih gelap memang menguntungkan.
Kesimpulannya, standar kecantikan sangat bervariasi baik dari budaya satu ke budaya yang lain dan dari waktu ke waktu. Di Indonesia, yang dianggap cantik juga berkembang secara bertahap. Sepanjang proses perkembangan itu, faktor yang berbeda dapat dipertimbangkan. Standar kecantikan yang awalnya didasarkan pada nilai-nilai tradisional digantikan oleh pengaruh media, industri kosmetik dan iklan yang mereka buat.
Di industri kosmetik Indonesia sendiri, produk paling populer dengan pendapatan tertinggi adalah produk pemutih, menunjukkan fakta bahwa ada banyak permintaan dari pasar, yang berarti bahwa banyak orang Indonesia menginginkan kulit yang lebih terang. Mereka itulah yang percaya kulit lebih terang lebih diminati dibandingkan dengan kulit yang lebih gelap, padahal sebenarnya banyak penelitian menyatakan bahwa kulit yang lebih gelap memang secara ilmiah bermanfaat bagi mereka yang tinggal di negara tropis yang terkena sinar matahari sepanjang tahun seperti Indonesia.
Daftar Bacaan
“Bradley University: Body & Beauty Standards”. Bradley.edu. N.p., 2016. Web. 9 Oct. 2016. Ahmed, S., 2007. MULTICULTURALISM AND THE PROMISE or HAPPINESS. New formations, 2008, p.63.
Indriati, E., 2005. SIKLUS HIDUP DAN KERAGAMAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KEDOKTERAN. Jablonski, N.G. and Chaplin, G., 2000. The evolution of human skin coloration. Journal of human evolution, 39(1).
Media, Kompas. “Hati-Hati, Krim Pemutih Wajah Bisa Sebabkan Kanker Kulit – Kompas.Com”. Health.kompas.com. N.p., 2016. Web. 28 Sept. 2016.
Post, The. “Chasing The Quintessential Indonesian Beauty”. The Jakarta Post. N.p., 2016. Web. 28 Sept. 2016.
Saraswati, L.A., 2010. Cosmopolitan whiteness: The effects and affects of skin-whitening advertisements in a transnational women’s magazine in Indonesia. Meridians: feminism, race, transnationalism, 10(2), pp.15-41.
Saraswati, L.A., 2012. ” Malu”: Coloring Shame and Shaming the Color of Beauty in Transnational Indonesia. Feminist Studies, 38(1).

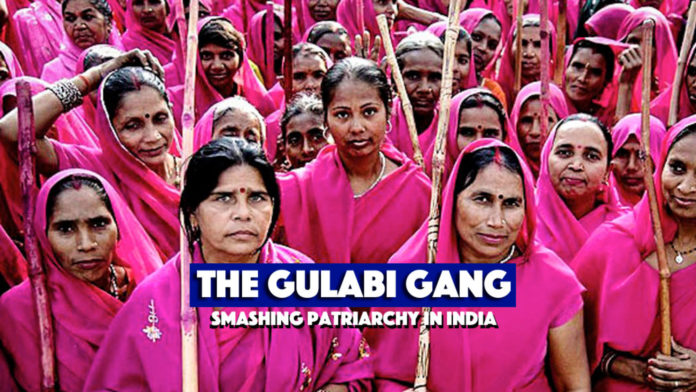



 Sejak tahun 2011 sampai sekarang, Samsara selalu mengikuti
Sejak tahun 2011 sampai sekarang, Samsara selalu mengikuti