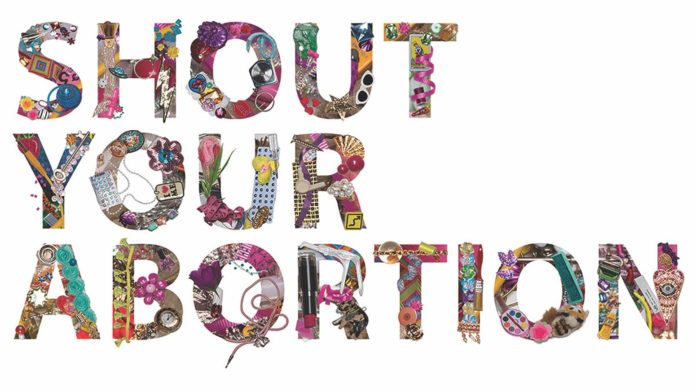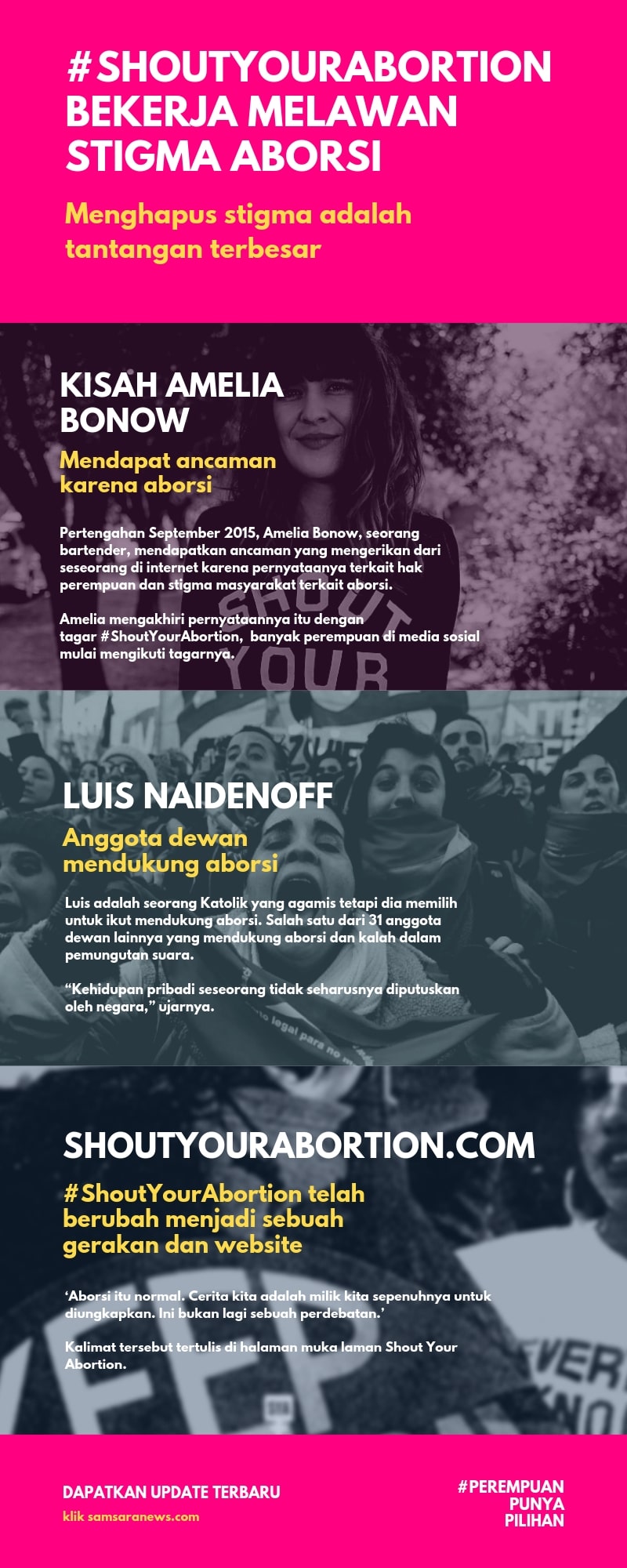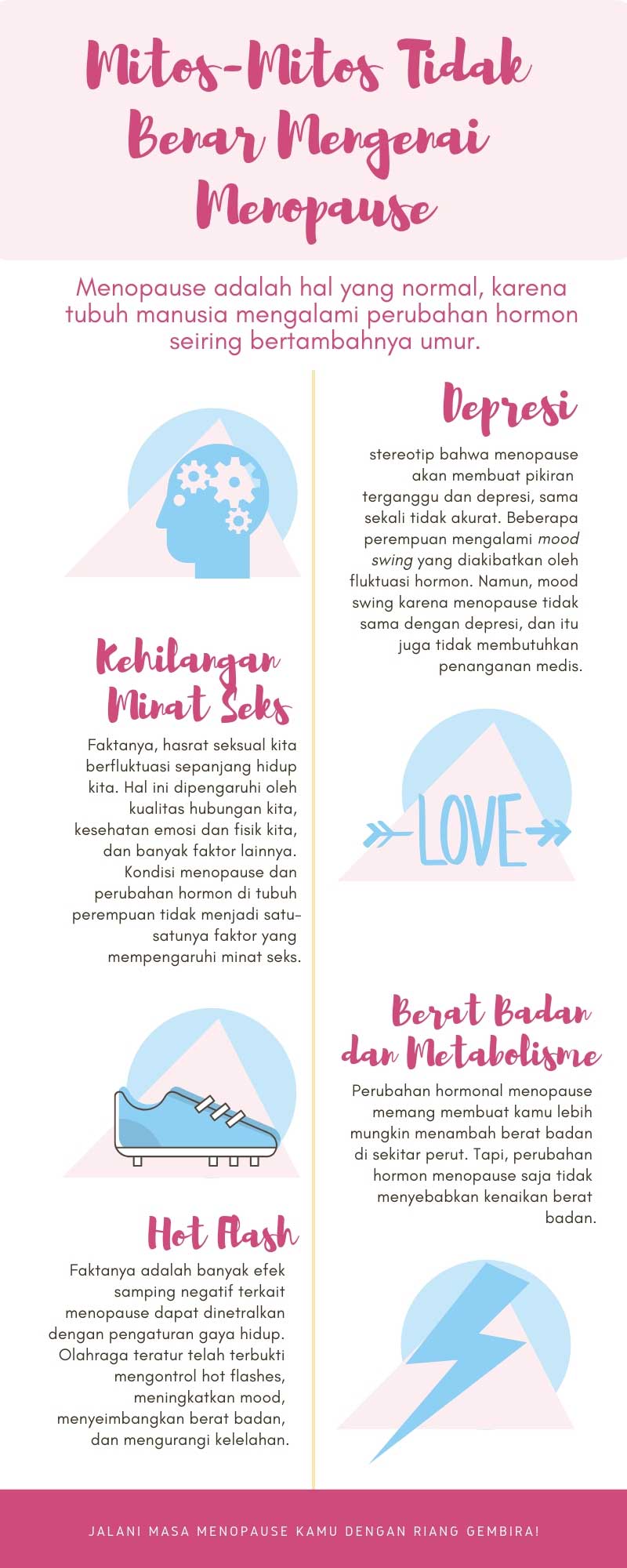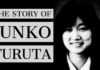Sebagian besar anak muda lebih percaya internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap tabu untuk dibicarakan, termasuk salah satunya adalah informasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka kemudian memilih alternatif yang paling mudah diakses saat ini: Google, untuk mencari tahu segala sesuatu. Pada tahun 2017 Youth Tech Health (YTH), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Oakland, California melakukan penelitian yang membenarkan kesimpulan ini. Sebanyak 21% dari responden mereka mengatakan bahwa informasi yang ditemukan melalui Google atau mesin pencari lain adalah ‘satu-satunya cara paling efektif untuk belajar tentang seks, seksualitas, dan kesehatan reproduksi.’
Tentu saja, internet bukannya tidak menyediakan sumber informasi yang dapat dipercaya, terlebih yang berkaitan dengan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Tetapi, daripada informasi yang kredibel, ada lebih banyak sumber di internet yang malah justru bisa menyesatkan pembaca. Ini jadi bumerang. Google dan mesin pencari lainnya memang dapat diandalkan tetapi tidak serta merta dapat dipercaya.
Seperti dikutip dari Healthline, ada beberapa sumber online yang menyediakan informasi akurat mengenai kesehatan seksual serta tidak menghakimi seperti Sex, Etc., Planned Parenthood, Scarleteen, dan Go Ask Alice. Tetapi, perlu diketahui bahwa semua situs tersebut menggunakan bahasa Inggris. Di Indonesia sendiri, situs terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang dapat dipercaya masih sangat sedikit, misalnya Angsa Merah Clinic, Samsaranews, Askinna, atau Tabu, yang menyatakan diri sebagai ruang belajar kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak muda Indonesia yang dapat diakses melalui Instagram.
Meski begitu, kecenderungan anak muda mengakses situs-situs kesehatan yang tidak akurat tidak lagi dapat terelakkan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Guttmacher Institute menyatakan bahwa dari 177 situs kesehatan seksual yang mungkin diakses oleh anak muda, 46% memuat informasi yang salah kaprah mengenai kontrasepsi dan 35% menyediakan informasi yang tidak akurat mengenai aborsi. Padahal, kekeliruan informasi seperti itu sangat merugikan. Informasi yang akurat mengenai hal tersebut penting bagi para siswa karena tidak hanya membantu mencegah mereka dari Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) dan penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS), tetapi juga dapat membantu memastikan kesejahteraan mereka.
Dengan banyaknya informasi yang salah kaprah ini, internet seharusnya tidak menjadi satu-satunya rujukan bagi para remaja jika ingin belajar mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Laura Lindberg, salah satu ilmuwan dan pakar kesehatan remaja di Guttmacher Institute mengatakan bahwa tidak masuk akal mengasumsikan remaja dapat menemukan cara mereka sendiri untuk memperoleh informasi yang akurat terkait kesehatan seksual dan reproduksi di internet. Sehingga, pendidikan seksual di sekolah seharusnya tetap menjadi prioritas utama.
“Kamu tidak bisa mengandalkan Google soal kesehatan. Kita perlu memastikan sumber daya lain tersedia bagi remaja,” katanya seperti dikutip dari Healthline.
Kontroversi Pendidikan Seks di Sekolah
Di Indonesia, kebijakan penerapan pendidikan seks di sekolah hampir selalu berujung kontroversi. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan seks bagi remaja justru dapat mendorong mereka melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Padahal, jika pendidikan ini diberikan yang terjadi justru adalah sebaliknya. Seperti dikutip dari Healthline, Guttmacher Institute pada tahun 2012 melakukan penelitian bersama Laura Lindberg dan menemukan fakta bahwa remaja lebih cenderung menunda hubungan seksual pertama mereka jika mereka belajar tentang seks dan pilihan terhadap kontrol kelahiran. Penelitian ini dilakukan kepada hampir lima ribu anak muda di Amerika Serikat dan hasilnya, mereka yang memperoleh pendidikan seks memilih menggunakan kondom saat berhubungan. Sementara itu, di Indonesia sendiri, menurut Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa pendidikan seksual telah masuk dalam kurikulum di sekolah tetapi materinya hanya pada pendidikan kesehatan reproduksi.
“Sebenarnya materi pendidikan kesehatan reproduksi sudah ada di K-13 (kurikulum belajar tahun 2013-red). Sudah lengkap semua, tetapi maunya sebagian masyarakat dieksplisitkan melalui pendidikan seks,” ujar Hamid seperti dikutip dari CNN Indonesia. Menurutnya, pendidikan seksual tidak perlu diterapkan di luar kurikulum selama pihak sekolah mampu mengajarkan materi kesehatan reproduksi sesuai dengan aturan.
Pendapat ini berlawanan dengan guru besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Sarlito Wirawan, yang mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan seks justru perlu diberikan secara mendetail kepada remaja agar mereka tahu bagaimana perilaku seks yang aman serta bahaya apa yang mengancam jika mereka melakukan seks yang tidak aman.
“Masyarakat yang tidak mengerti seks tidak akan tahu bagaimana cara menghindari bahaya penyalahgunaan seks. Begitu juga ABG yang tidak tahu tentang seks, tahu-tahu sudah KTD. Bingung lah dia dan lari ke aborsi ilegal,” jelas Prof. Sarlito, seperti dikutip dari Economica. Ia juga menambahkan bahwa pendidikan seks tidak boleh didasarkan pada kecurigaan akan mendorong anak muda melakukan hubungan seksual sebelum saatnya. Pandangan seperti ini, menurutnya, justru hanya akan melanggengkan stigma bahwa seks adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Terkait hal ini, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Mariana Amiruddin, juga mengatakan hal yang sama. Seks jadi dianggap tabu karena masyarakat Indonesia justru cenderung mengaitkan persoalan ini dengan moral.
“Orang Indonesia tidak mengerti bahwa pendidikan bukan soal kepercayaan, tetapi soal kebenaran yang bisa dibuktikan. Seks itu bukan soal moral. Akan tetapi, diri kita ini sebagai makhluk seksual kita harus tahu fungsinya bagaimana, prakteknya bagaimana, pada usia berapa, tumbuh seperti apa dan bekerja seperti apa,” ujar Mariana seperti dikutip dari Economica.
Pendidikan seks yang komprehensif pada dasarnya tidak hanya mengajarkan para siswa tentang fungsi alat reproduksi tetapi juga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai apa itu seks dan seksualitas. Pendidikan ini mencakup informasi yang sangat luas mengenai jenis kelamin, gender, hubungan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, serta lebih banyak lagi. Tentu saja, pada akhirnya pemahaman yang komprehensif dapat mendorong anak muda untuk bersikap lebih toleran kepada sesama manusia dengan berbagai macam keragaman serta kompleksitas gender dan orientasi seksualnya




 Faktor lain yang melanggengkan budaya patriarki adalah agama. Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama, faktor agama sangatlah penting dalam menentukan laju keseharian, termasuk dalam melanggengkan budaya patriarki. Ayu Utami dalam novel
Faktor lain yang melanggengkan budaya patriarki adalah agama. Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama, faktor agama sangatlah penting dalam menentukan laju keseharian, termasuk dalam melanggengkan budaya patriarki. Ayu Utami dalam novel